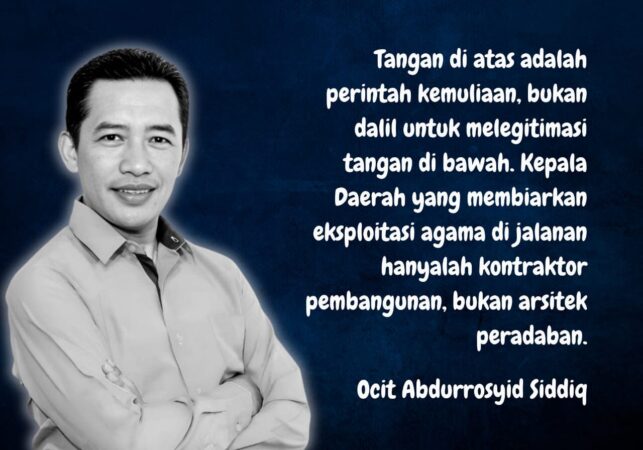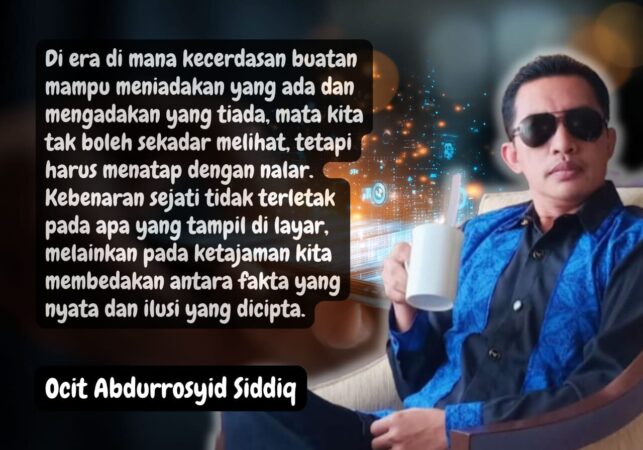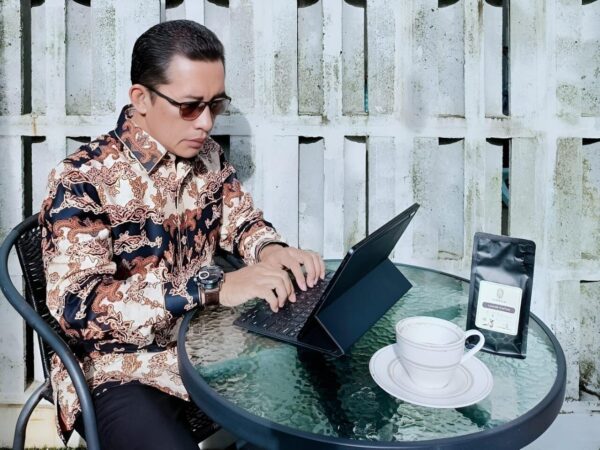Oleh : Dede Sudiarto
( bid.Pendidikan ICMI Banten )
Sistem pendidikan Indonesia pada dasarnya dibangun di atas fondasi filosofi yang sangat mulia. Konstitusi telah mengamanatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara, dan program wajib belajar 12 tahun dirancang untuk mencetak generasi cerdas, beriman, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Secara prinsip, arah kebijakan ini sudah ideal, bahkan menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia, misalnya, baru mencapai 9,22 tahun atau setara lulus SMP. Di Papua Pegunungan, angka ini bahkan hanya 5,1 tahun, menunjukkan betapa jurang ketimpangan akses pendidikan masih menganga lebar.
Salah satu kendala utama terletak pada infrastruktur pendidikan yang belum merata. Indonesia memiliki lebih dari 216 ribu sekolah dengan jutaan guru dan puluhan juta peserta didik, tetapi daya tampung dan fasilitas yang tersedia sering kali tidak seimbang. Hanya sekitar 14 persen SMA yang memiliki laboratorium memadai, sementara rasio rombongan belajar kerap melebihi standar ideal. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, terutama di daerah terpencil yang sering kekurangan guru berkualitas dan fasilitas pendukung.
Masalah daya tampung semakin terasa ketika penerimaan peserta didik baru berlangsung. Di kota besar seperti Jakarta, hanya sekitar 47 persen calon siswa SMP yang dapat diterima di sekolah negeri, dan untuk SMA/SMK persentasenya lebih rendah lagi, sekitar 20 persen. Keterbatasan ini menimbulkan kompetisi yang kerap dianggap tidak adil, meskipun pemerintah telah menerapkan sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi. Kuota dan pembagian jalur tidak selalu mampu menjawab persoalan distribusi sekolah yang timpang, sehingga banyak siswa terpaksa mencari alternatif lain dengan biaya lebih tinggi.
Selain persoalan struktural, tantangan lain muncul dari sisi motivasi belajar siswa. Tidak sedikit anak masuk sekolah bukan karena dorongan intrinsik untuk menimba ilmu, melainkan sekadar mengejar ijazah sebagai legitimasi formal. Sekolah pada akhirnya dipandang sebagai “pintu administratif” ketimbang ruang pembentukan karakter dan pengetahuan. Kondisi ini semakin diperparah dengan sistem pembelajaran yang masih menekankan hafalan, sementara minat, kreativitas, dan pemikiran kritis kurang diberi ruang berkembang.
Problem pendidikan Indonesia juga menyentuh dimensi kebebasan guru dalam mendidik. Pada kenyataannya, guru tidak sepenuhnya merdeka untuk memberikan perlakuan berbeda sesuai kebutuhan tiap anak. Padahal setiap siswa memiliki latar belakang, karakter, dan gaya belajar yang unik, bahkan sering kali dipengaruhi budaya lokal. Sayangnya, pendekatan khas yang berakar dari tradisi daerah terkadang disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, ruang kreativitas guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran menjadi sempit, dan pendidikan kehilangan nuansa personal yang seharusnya justru memperkaya proses belajar.
Kebijakan wajib belajar 12 tahun tentu sangat penting, tetapi tanpa persiapan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan akses, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi jargon. Pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola penerimaan siswa agar lebih transparan dan tidak menimbulkan praktik jual beli bangku sekolah. Pada saat yang sama, orientasi kurikulum harus diperkuat agar siswa tidak hanya mengejar nilai ujian, melainkan juga menemukan makna belajar dalam kehidupan nyata.
Jika jurang antara filosofi dan realitas ini tidak segera dijembatani, pendidikan di Indonesia akan terus berjalan di tempat: luhur dalam gagasan, tetapi tertatih dalam pelaksanaan. Padahal, hakikat pendidikan bukan sekadar mendistribusikan ijazah, melainkan membuka jalan bagi setiap anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara adil dan bermakna.