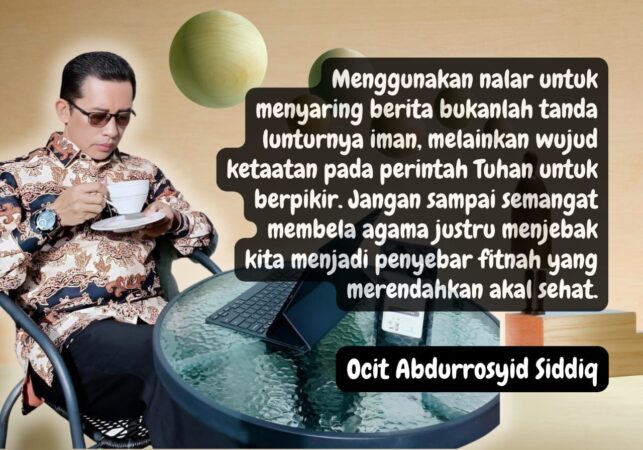Ocit Abdurrosyid Siddiq
Sejatinya, Tuhan dan agama tidak membutuhkan pembelaan dari siapa pun. Dalam perspektif transenden, Tuhan adalah Dzat Yang Maha Kuasa, Pemilik Semesta yang kekuasaan-Nya melampaui segala batas imajinasi manusia. Dia mampu menjaga kesucian firman-Nya tanpa bantuan tangan-tangan kecil makhluk bernama manusia. Namun, realitas keberagamaan tidak berhenti di langit.
Ketika agama turun ke bumi dan dianut oleh manusia, ia memasuki ranah imanen. Di sinilah muncul rasa kepemilikan, cinta, dan tanggung jawab. Seorang penganut agama merasa terikat tidak hanya untuk meyakini, tetapi juga untuk mendakwahkan dan menjaga kehormatan keyakinannya. Naluri ini wajar, bahkan manusiawi.
Namun, persoalan muncul ketika semangat pembelaan itu tidak dibarengi dengan nalar yang jernih dan prinsip kejujuran. Di sinilah sering terjadi disrupsi pemahaman; sebuah paradoks di mana seseorang berniat memuliakan “Kebenaran” (Al-Haqq), namun ironisnya dilakukan dengan cara-cara yang “Batil” (salah/bohong).
Kita sering melihat fenomena di mana “iman” dijadikan tameng untuk mematikan rasio. Padahal, Islam sendiri menempatkan akal pada posisi yang sangat mulia. Ayat-ayat Afala ta’qilun (apakah kamu tidak berakal) atau Afala tatafakkarun (apakah kamu tidak berpikir) bertebaran dalam kitab suci sebagai tantangan terbuka bagi manusia untuk menggunakan logikanya. Sayangnya, tantangan ini kerap diabaikan demi sebuah euforia semu bernama “kebanggaan golongan”.
Sebagai contoh nyata dari fenomena ini adalah munculnya klaim-klaim pseudo-sejarah yang tidak didasari oleh metodologi ilmiah, namun disebarluaskan secara masif karena dianggap “menguntungkan” citra agama. Kita tentu ingat narasi yang sempat populer beberapa waktu lalu yang mengklaim bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman.
Narasi ini dibangun dengan mencocok-cocokkan (cocoklogi) relief candi dengan deskripsi istana Sulaiman dalam kitab suci, tanpa mengindahkan fakta arkeologis, uji karbon batu, maupun catatan sejarah Wangsa Syailendra yang jelas-jelas bercorak Buddha.
Bagi sebagian orang, mempercayai narasi ini memberikan kepuasan batin; seolah-olah hal itu membuktikan bahwa jejak kenabian sudah ada di Nusantara jauh sebelum masa sejarah yang diakui. Namun, jika ditelisik dengan nalar yang dingin, klaim tanpa bukti ini justru merendahkan integritas umat Islam sendiri.
Kita seolah menjadi umat yang memiliki inferiority complex (rasa rendah diri), sehingga perlu “mencuri” sejarah dan kebudayaan orang lain untuk merasa besar. Padahal, tanpa mengklaim Borobudur pun, Islam sudah memiliki peradaban yang agung. Membela agama dengan memalsukan sejarah adalah sebuah pengkhianatan terhadap kebenaran itu sendiri.
Setali tiga uang dengan kasus di atas, muncul pula narasi yang mengklaim bahwa pahlawan nasional Kapitan Pattimura memiliki nama asli Ahmad Lussy, seorang Muslim yang taat. Klaim ini berusaha menggeser sosok Thomas Matulessy yang selama ini tercatat dalam sejarah. Sekali lagi, semangatnya adalah “islamisasi sejarah”.
Namun, ketika dituntut bukti otentik—seperti catatan silsilah yang valid atau arsip kolonial yang mendukung—klaim ini seringkali gagap. Membela kehormatan pahlawan muslim tentu baik, namun memaksakan tokoh sejarah menjadi muslim tanpa dasar fakta adalah tindakan yang tidak kaffah dalam beragama. Bukankah Islam mengajarkan kejujuran?
Di sisi lain, fanatisme buta yang mematikan rasio tidak hanya melahirkan klaim kepemilikan sejarah, tetapi juga melahirkan paranoia atau ketakutan yang tidak berdasar (xenophobia). Hal ini terlihat jelas dalam mudahnya umat terpancing oleh kabar bohong (hoaks) yang bernada provokatif.
Masih segar dalam ingatan kita sebuah video yang viral di media sosial, memperlihatkan suasana di dalam Masjid Istiqlal. Dalam video tersebut, tampak sekelompok orang bernyanyi dengan mengenakan pakaian serba merah dan putih. Narasi yang menyertai video tersebut sangat provokatif: “Masjid Istiqlal dipakai untuk perayaan Natal”. Sontak, gelombang kemarahan muncul di kolom komentar. Caci maki berhamburan, menuduh pengelola masjid telah murtad dan membiarkan rumah Allah ternoda.
Padahal, jika nalar digunakan sedikit saja untuk melakukan verifikasi (tabayyun), fakta yang ditemukan sangatlah berbeda. Acara tersebut adalah perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh sebuah majelis taklim ibu-ibu pengajian. Mereka menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan mengenakan seragam merah putih sebagai wujud nasionalisme. Tidak ada ritual agama lain, tidak ada perayaan Natal.
Kasus Istiqlal ini adalah cermin betapa rapuhnya “pertahanan nalar” kita ketika sentimen agama disentuh. Kita begitu sibuk membela “kulit” agama, hingga lupa pada “isi” ajarannya yang memerintahkan untuk memeriksa kebenaran berita sebelum menghakimi.
Dalam kasus ini, siapa yang sebenarnya menistakan agama? Apakah mereka yang dituduh, atau justru mereka yang menyebarkan fitnah dan mereka yang percaya tanpa check and recheck?
Contoh lain yang tak kalah legendaris adalah cerita tentang astronot Neil Armstrong yang dikabarkan mendengar suara azan di bulan, lalu masuk Islam. Cerita ini diulang-ulang di mimbar-mimbar selama puluhan tahun sebagai bukti kebenaran Islam. Padahal, Armstrong sendiri telah berkali-kali membantahnya, dan pihak berwenang pun telah mengklarifikasi bahwa itu tidak benar.
Mengapa kita begitu haus akan pengakuan dari seorang astronot Barat untuk meyakini kebenaran azan? Apakah iman kita begitu tipis sehingga butuh validasi dari dongeng yang tidak nyata?
Ada disparitas (kesenjangan) yang menganga antara Islam yang ideal dengan perilaku muslim yang khilaf. Islam itu sempurna, ajarannya paripurna. Namun muslim adalah manusia biasa yang bisa terjebak dalam emosi, kebodohan, dan ego sektoral.
Ketika seorang muslim membela agamanya dengan cara menyebar hoaks atau mengklaim sejarah tanpa bukti, ia sedang mempertontonkan wajah muslim yang tidak mashum (tidak terpelihara dari dosa), bukan wajah Islam yang suci.
Prinsip qulil haq walau kaana murran—katakanlah yang benar walaupun itu pahit—harus menjadi pegangan. Jika data sejarah mengatakan Borobudur adalah candi Buddha, kita harus mengakuinya dengan jantan. Itu adalah kebenaran fakta. Jika video di Istiqlal adalah acara pengajian, kita harus membelanya dari fitnah, meskipun narasi fitnah itu datang dari saudara seiman sendiri.
Membela agama tidak harus dengan otot yang tegang atau jari yang sibuk membagi tautan provokatif. Membela agama bisa dilakukan dengan muhasabah; sebuah otokritik ke dalam diri. Muhasabah bukanlah cemoohan terhadap agama sendiri, melainkan upaya membersihkan debu-debu kebodohan yang menempel pada praktik keberagamaan kita.
Ketika kita mampu berpikir jernih, menggunakan rasio sebagai alat ukur kebenaran universal, kita mungkin akan menemukan titik temu dengan mereka yang berbeda iman. Kesamaan pandangan dalam melihat fakta—misalnya sepakat bahwa hoaks Istiqlal itu salah—bukan berarti iman kita tergadai. Itu justru menunjukkan bahwa nalar sehat (common sense) adalah anugerah Tuhan yang dimiliki oleh seluruh umat manusia.
Maka, mari kita ubah cara pandang kita. Tuhan tidak butuh dibela dengan kebohongan. Agama tidak butuh ditinggikan dengan merendahkan fakta. Kemuliaan agama justru akan terpancar ketika penganutnya menjadi pribadi yang paling jujur dalam sejarah, paling teliti dalam menerima berita, dan paling adil dalam menilai perkara.
Itulah sebenar-benarnya pembelaan; sebuah pembelaan yang dilatari oleh akal yang sehat dan hati yang bening, selaras dengan tuntunan Ilahi.
“Menggunakan nalar untuk menyaring berita bukanlah tanda lunturnya iman, melainkan wujud ketaatan pada perintah Tuhan untuk berpikir. Jangan sampai semangat membela agama justru menjebak kita menjadi penyebar fitnah yang merendahkan akal sehat.”
*
Tangerang, Jumat, 2 Januari 2026
Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi PB. Mathlaul Anwar, alumni Prodi Aqidah dan Filsafat IAIN SGD Bandung