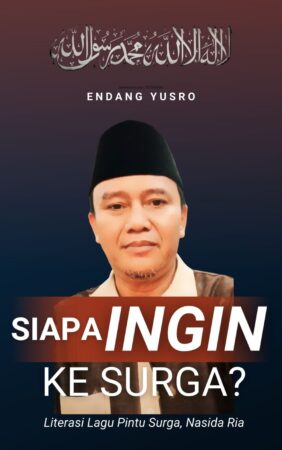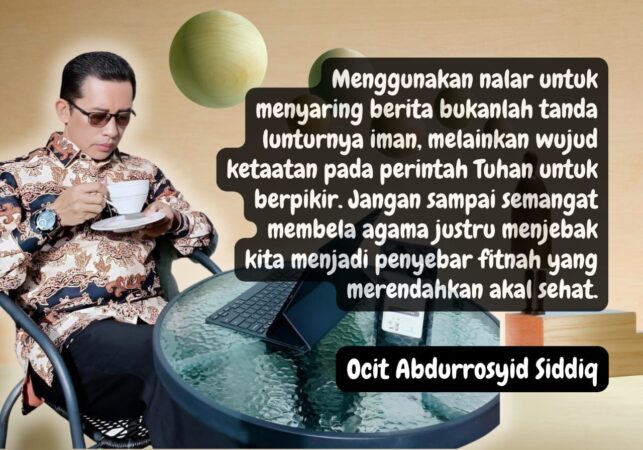Oleh : Adung Abdul Haris
I. Pendahuluan
Sekitar tahun 1996-an, saat itu sedang buming khususnya di kalangan para akademisi di negeri ini, yaitu terud memperdebatkan soal tesis dari Samuel P. Huntington (ilmuan politik Amerika). Bahkan saat itu terjadi polemik yang begitu kencang di forum-forum diskusi ilmiah, dan kebetulan penulis juga saat itu ikut kecipratan untuk mendiskusikan soal tesis dari Samuel P. Hutington berjudul “Benturan Peradaban” yang sangat kontroversi saat itu. Sementara penulis sendiri saat itu kebetulan sedang duduk disemester empat (di perguruan tinggi) dan sedang haus-hausnya untuk mengikuti diskursus keilmuan dan sedang kencang-kencangnya untuk merambah pada proses petualangan dunia intelektual. Menurut Samuel P. Hutinton (sang penulis tesis yang kontroversial itu), bahwa konflik di dunia yang akan terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor ideologis atau ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh apa yang disebut sebagai “Benturan peradaban” (benturan Peradaban) (lihat Samuel P. Huntington, 1993: 22 -49 dan 2003).
Huntington menjelaskan, bahwa benturan peradaban akan mewarnai dan mendominasi politik global. Menurutnya, identitas peradaban akan semakin penting pada masa akan datang dan dunia akan terbentuk dalam ukuran besar oleh interaksi di antara tujuh atau delapan peradaban utama: Barat, Konfuius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia Ortodoks, Amerika Latin dan mungkin Afrika. Konflik yang paling penting pada masa akan datang menurut Hutinton, yaitu terjadi diantara garis budaya yang memisahkan satu peradaban dengan yang lain. Beberapa negara yang lebih suka bergabung dengan Barat mengajukan westernisasi secara penuh, seperti Jepang, Rusia, negara lain di Eropa Timur dan Amerika Latin. Sementara yang tidak tergabung dengan Barat adalah, mereka menerima modernisasi tetapi menolak westernisasi. Namun, sebetulnya dua tahun sebelum Huntington membuat polemis lewat tesisnya itu, saat itu sudah ada tesis serupa yang dilontarkan oleh Buzan. Hanya karena tidak ditulis secara provokatif sehingga tidak populer gaungnya. Barry Buzan membuat sketsa ciri-ciri utama dari pola baru hubungan keamanan global yang muncul setelah transformasi besar tahun 1989-1990. Menurutnya, terdapat empat ciri dasar dari bentuk hubungan baru antara beberapa negara, yaitu : Pertama, munculnya struktur kekuasaan multipolar di samping pusat bipolar yang telah ada sejak perang dingin. Kedua, suatu tingkat pembagian dan perpecahan ideologi yang lebih kecil. Ketiga, kecenderungan dominasi6 internasional dari kelompok kapitalis negara-negara yang menaruh perhatian pada masalah keamanan dan perubahan. Keempat, sebuah konsolidasi kekuatan masyarakat sipil internasional. Bahkan, perubahan-perubahan di pusat (negara-negara industri) akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan politik, militer, ekonomi dan sosial dari pinggiran (negara-negara non-industri). Akibat-akibat inilah yang disebut Buzan sebagai “Benturan Dari Identitas Peradaban” yang berselisih, yang sangat mencolok antara Barat dan Timur (Islam).
II. Efistema “Tesis” Samuel P. Hutinton Yang Kontroversi Itu
Benturan peradaban adalah sebuah tesis dari Samuel P. Hutinton, yang memaparkan, bahwa ketika terjadi benturan peradaban konon kata Hutington, maka identitas budaya dan agama masyarakat akan menjadi sumber utama7 konflik di dunia, yaitu pasca perang dingin (antara Amerika denga Rusia). Ilmuwan politik Amerika Samuel P. Huntington di dalam sebuah tesisnya itu ia berpendapat, bahwa perang dimasa depan tidak akan terjadi antar negara, tetapi akan terjadi antar budaya. Hal itu awalnya ia diajukan dalam sebuah kuliah pasa tahun 1992 di “American Enterprise Institute”, yang kemudian dikembangkan dalam sebuah artikel “Foreign Affairs” tahun 1993, yautu berjudul “Benturan Peradaban”?. Sementara tesis Hutington itu muncul adalah sebagai tanggapan terhadap buku tahun 1992, yaitu karya dari mantan muridnya, Francis Fukuyama, yang berjudul “The End of History and the Last Man”.
Huntington kemudian mengembangkan tesisnya dalam sebuah buku tahun 1996 berjudul “Benturan Peradaban dan Pembuatan Ulang Tatanan Dunia”. Namun, frasa itu sendiri sebelumnya digunakan oleh Albert Camus pada tahun 1946, oleh Girilal Jain dalam analisisnya tentang pertikaian Ayodhya pada tahun 1988. Kemudian Bernard Lewis, ia menulis sebuah artikel berjudul “The Atlantic Monthly”, edisi September tahun 1990, kemudian artikel berikutnya berjudul “ The Roots of Muslim Rage”. Bahkan sebelumnya, frasa itu juga muncul dalam sebuah buku pada tahun 1926, yaitu tentang Timur Tengah oleh Basil Mathews: “Young Islam on Trek: A Study in the Clash of Civilizations”. Ungkapan itu berasal dari “benturan budaya ”, yang sudah digunakan selama periode kolonial.
Latar belakang munculnya tesia Huntington itu, yaitu ia memulai pemikirannya dengan mensurvei berbagai teori tentang hakikat politik global pada periode pasca perang dingin. Beberapa ahli teori dan penulis berpendapat bahwa hak asasi manusia, demokrasi liberal, dan ekonomi pasar bebas kapitalis telah menjadi satu-satunya alternatif ideologis yang tersisa bagi negara-negara di dunia pasca perang dingin. Secara khusus, Francis Fukuyama berpendapat bahwa dunia telah mencapai ‘akhir sejarah’ dalam pengertian Hegelian. Namun, Huntington percaya bahwa meskipun zaman ideologi telah berakhir, namun dunia hanya kembali ke keadaan normal yang dicirikan oleh konflik budaya. Dalam tesisnya, ia berpendapat bahwa poros utama konflik dimasa depan akan berada di sepanjang garis budaya. Sebagai tambahan, ia berpendapat bahwa konsep peradaban yang berbeda, sebagai tingkatan tertinggi identitas budaya, akan semakin berguna dalam menganalisis potensi konflik. Di akhir artikelnya di “Foreign Affairs” tahun 1993. Huntington menulis, “Ini bukan untuk mendukung keinginan akan konflik antar peradaban. Ini untuk mengemukakan hipotesis deskriptif tentang seperti apa masa depan nanti”.
Selain itu, benturan peradaban, bagi Huntington, merupakan perkembangan sejarah. Karena, dimasa lalu, sejarah dunia terutama tentang pertikaian antara raja, bangsa, dan ideologi, seperti yang terlihat dalam peradaban Barat. Namun setelah berakhirnya perang dingin, makabpolitik dunia akan bergerak ke fase baru, yakni dimana peradaban non-Barat tidak lagi menjadi penerima eksploitasi peradaban Barat, tetapi telah menjadi aktor penting tambahan yang bergabung dengan Barat untuk membentuk dan menggerakkan sejarah dunia. Peradaban Islam, tulis Huntington, adalah yang paling komflikitit. Karena, orang-orang di dunia Arab tidak memiliki anggapan umum yang sama dengan dunia Barat. Keterikatan utama mereka adalah pada agama mereka, bukan pada negara-bangsa mereka. Budaya mereka tidak ramah terhadap cita-cita liberal tertentu, seperti pluralisme, individualisme, dan demokrasi.
Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh David Brooks, Huntington dengan tepat meramalkan bahwa rezim-rezim Arab yang kuat itu rapuh dan terancam oleh massa pemuda-pemudinya yang menganggur. “Dunia Muslim memiliki perbatasan yang berdarah, lanjutnya. Ada perang dan ketegangan di mana dunia Muslim berkonflik dengan peradaban-peradaban lain.
Bahkan jika rezim-rezim yang bobrok itu tumbang, menurutnya, masih akan ada benturan mendasar antara peradaban-peradaban Islam dan Barat. Negara-negara Barat sebaiknya menjaga jarak dari urusan-urusan Muslim. Semakin banyak kedua peradaban itu bercampur, maka semakin buruk ketegangannya”, tulis Brooks.
Sementara menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Azmi Bishara, bahwa dogma yang berlaku di Tiongkok dan Rusia melihat penyebaran demokrasi sebagai perpanjangan dari peradaban Barat, dan karenanya, hal itu sebagai alat hegemoni Barat. Singkatnya, ini berarti bahwa, secara global, teori benturan peradaban saat ini sedang diadopsi oleh kedua kekuatan besar, khususnya Rusia. Bishara berpendapat bahwa jika Huntington masih hidup saat ini, ia mungkin akan terkejut dengan pernyataan saya bahwa benturan peradaban telah menjadi doktrin hubungan internasional Rusia dan Tiongkok.
Bishara juga menggarisbawahi bahwa “Jika Huntington berpikir keras, ia akan menganggap gagasan itu logis. Teorinya tentang benturan peradaban telah diadopsi di AS oleh kaum nasionalis konservatif sayap kanan, yang percaya pada politik kekuasaan dalam hubungan internasional. Justru kekuatan-kekuatan yang percaya pada kredo politik inilah yang memerintah Rusia saat ini. Mereka adalah kaum nasionalis Rusia konservatif sayap kanan. Hal yang sama berlaku untuk Tiongkok, meskipun model kebijakan ekonomi dan ambisi di tingkat dunia berbeda”. Sementar Rogers Brubaker mengatakan dalam sebuah artikelnya, bahwa populisme peradaban pertama kali dirintis satu setengah dekade lalu oleh politikus Belanda Pim Fortuyn. “Tentu saja Fortuyn bukanlah orang pertama yang memanfaatkan kecemasan masyarakat tentang imigrasi atau menyalahkan imigran atas kejahatan dan kekacauan perkotaan. Namun, ia berinovasi dengan menggabungkan retorika anti-imigran (dan khususnya anti-Muslim) dengan posisi liberal dalam isu-isu sosial, khususnya hak-hak kaum gay. Dengan bangga ia menyebut dirinya sebagai ‘Samuel Huntington dalam politik Belanda,’ Fortuyn memunculkan momok ‘benturan peradaban’ di Eropa antara apa yang disebutnya sebagai ‘budaya humanistik Yahudi-Kristen,’ yang liberal dan terbuka, dan budaya Islam, yang ia gambarkan sebagai budaya terbelakang dan terpinggirka, khususnya dalam ranah gender dan seksualitas”, tegas Brubaker.
Menurut Brubaker, dalam menghadapi bahaya itu, penting untuk menegaskan melawan perspektif Huntington yang vulgar yang diadopsi oleh kaum populis peradaban bahwa peradaban bukanlah entitas yang bersatu dengan esensi abadi yang saling bertentangan satu sama lain. Peradaban adalah bidang praktik dan wacana yang luas, beragam, tidak teratur, dan terus berkembang. Menganggap adanya benturan peradaban berarti mengabaikan benturan yang lebih penting dalam peradaban.
III. Benturan Peradaban Huntington Dan Tren Peningkatan Fundamentalisme Religius
Menurut para memikur serta orang-orang yang mendukung tesis dari Samuel P. Hutington, mereka berpendapat bahwa sejak dari awal, Huntington telah menekankan tesisnya, bahwa sumber fundamental dari konflik-konflik di dunia tidak lagi berlatarbelakang ideologis maupun ekonomis, melainkan kultural. Lebih jauh lagi menurut pemikir dan pendukung tesis Hutington, bahw pembagian antara manusia yang dibawa oleh perbedaan kelompok-kelompok peradaban dan kebangsaan menandai evolusi konflik dunia modern. Sementara negara tetap menjadi aktor terkuat dalam hubungan global, benturan peradaban (clash of civilizations) ini akan mendominasi politik global. Ia berbeda dari konflik-konflik yang muncul sejak berlakunya sistem internasional modern bawaan Traktat Westphalia yang mana dulunya didominasi oleh pertarungan antar monarki yang berusaha memperluas birokrasi atau kekuatan ekonomi merkantilisnya yang menjadi pola konflik hingga abad ke-19. Sekalipun berbeda dari konflik-konflik ideologis yang dapat kita lihat antar komunisme, fasisme-Nazisme dan demokrasi liberal, dan antara komunisme dan demokrasi liberal yang diwakili dua kekuatan besar Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin memulai politik internasional untuk bergerak ke arah interaksi antara peradaban Barat non Barat dan di antara (among) peradaban non Barat itu sendiri. Dalam politik peradaban, pemerintahan dan rakyat dari peradaban non Barat tidak lagi merupakan objek sejarah atau target dari kolonialisme Barat, tetapi bergabung menjadi penggerak dan pembentuk dari sejarah.
Dalam mengelompokkan negara-negara ke dalam sebuah tipologi peradaban, Huntington lebih mengesampingkan sistem politik atau perkembangan ekonomi dan menekankan pada konteks budaya dan peradaban. Peradaban sendiri ia maknai sebagai entitas kultural yang mana mencakup wilayah, komunitas etnis, kebangsaan, dan kelompok religius yang memiliki budaya yang “distinct” pada tingkatan yang berbeda dalam heterogenitas kultural.
Budaya pedesaan di selatan Italia boleh jadi berbeda dari pedesaan di utara Italia, namun keduanya tetap berbagi kesamaan budaya Italia yang membedakannya dari pedesaan di Jerman. Komunitas Eropa, sebagai gantinya, juga turut berbagi kesamaan fitur kebudayaan yang membedakan mereka dari komunitas Arab atau Cina. Sebuah peradaban merupakan bentuk pengelompokan kebudayaan tertinggi dengan tingkatan terluas dari identitas budaya yang didefinisikan oleh kesamaan elemen objektif (bahasa, sejarah, agama, adat, institusi, dan identifikasi diri yang subjektif). Setelah membagi peradaban menjadi tujuh divisi (Barat, Konfusian, Jepang, Islam, Hindu, Slavik-Ortodoks, dan Amerika Latin atau kemungkinan Afrika), Akhirnya, Huntington menyatakan enam alasan mengapa peradaban-peradaban ini akan berbenturan.
A. Peta Peradaban Huntington
Pertama, perbedaan diantara peradaban tidak saja nyata, melainkan juga mendasar. Peradaban-peradaban ini dibedakan dari sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang terpenting agama. Orang-orang dari peradaban yang berbeda-beda memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat hubungan antara manusia dan Tuhan, individu dan kelompok, negara dan warga negara, serta kepentingan relatif dari hak, tanggung jawab, kebebasan dan wewenang, kesetaraan dan hierarki yang menjadi lebih fundamental daripada ideologi politik oleh sebab perbedaan-perbedaan itu merupakan produk dari proses perjalanan berabad-abad. Berbeda tidak selalu berarti konflik, dan konflik tidal selalu berarti kekerasan. Namun selama berabad-abad, perbedaan diantara peradaban telah menghasilkan konflik-konflik penuh kekerasan dan berkepanjangan. Kedua, dunia menjadi semakin mengecil. Meningkatnya interaksi diantara orang dengan peradaban yang berbeda akhirnya meningkatkan kesadaran peradaban (civilization consciousness) dan awas (awareness) terhadap persamaan dan perbedaan di dalamnya.
Lebih dari itu menurut Samuel P. Hutington, bahwa konflik di masa depan akan lebih banyak terjadi di sepanjang “fault lines” kebudayaan yang memisahkan peradaban-peradaban. Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia, akhirnya memisahkan orang dari identitas lokal yang telah berlangsung lama (longstanding cultural identity). Hal itu juga terus melemahkan negara-bangsa sebagai sumber bagi identitas, yang mana celah itu kemudian banyak diisi oleh agama-agama dunia dalam bentuk gerakan (movement) yang dilabeli sebagai fundamentalis. Gerakan semacam itu dapat dijumpai pada Kekristenan Barat, Yudaisme, hingga Islam. Kebangkitan rohani agama (the revival of religion) atau “la revanche de Dieu” menyediakan basis bagi identitas dan komitmen yang melampaui batas nasional dan menyatukan peradaban-peradaban.
Keempat, pertumbuhan kesadaran peradaban (civilization-consciousness) itu, akhirnya ditunjang oleh peran ganda Barat. Di satu sisi, Barat berada pada puncak kekuasaan yang kemudian menghasilkan adanya bentuk-bentuk de-westernisasi yang berupaya “return to the roots” yang secara harfiah berarti kembali ke akar, yang kerapkali melanda peradaban-peradaban non-Barat. Upaya itu dapat kita lihat pada kasus Asianisasi di Jepang, warisan Nehru untuk Hinduisasi di India, debat antara westernisasi dan Rusianisasi di Rusia, dan kegagalan gagasan Barat mengenai sosialisme dan nasionalisme sehingga adanya re-islamisasi di Timur Tengah. Barat yang berada di puncak kekuatan menghadapi non-Barat yang semakin memiliki keinginan, kehendak, dan sumber daya untuk membentuk dunia dengan cara-cara non-Barat. De-westernisasi dan pribumisasi (indigenization) elite terjadi di banyak negara non-Barat, namun pada saat bersamaan, budaya, gaya, dan kebiasaan Barat, biasanya Amerika, menjadi lebih populer diantara massa rakyat. Kelima, karakteristik dan perbedaan budaya lebih sukar berubah dan dikompromikan serta dipecahkan daripada politik atau ekonomi.
Pada masa Uni Soviet misalnya, seorang komunis dapat saja berubah menjadi seorang demokrat, yang kaya menjadi miskin dan yang miskin bisa menjadi kaya, akan tetapi orang Rusia tidak bisa menjadi orang Estonia (dalam artian etnis) atau orang Azeri pun tidak bisa menjadi orang Armenia dan seterusnya. Dalam konflik kelas dan politik, seseorang masih dapat berganti keberpihakan. Namun terhadap pertanyaan “what are you”, jawabannya adalah sesuatu yang “given” dan tidak dapat diganti. Lebih-lebih mengenai agama, seseorang bisa saja terlahir dari orang tua berkebangsaan Perancis dan Arab sehingga secara etnis, keturunannya merupakan percampuran dari keduanya, namun seseorang tidak bisa menjadi setengah Katolik dan setengah Islam. Keenam, peningkatan regionalisme ekonomi yang semakin memperkuat kesadaran peradaban (civilzations-consciousness) itu memang lebih berhasil jika berakar dalam kesamaan peradaban, sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa Komunitas Eropa berbagi fondasi budaya Eropa dan Kekristenan Barat yang ketiganya merupakan unsur tidak terpisahkan pembentuk peradaban negara-negara di kawasan Eropa.
IV. Tesis Huntington Dan Infiltrasi Peradaban
Bagi kelompok pemikir yang jelas-jelas menolak tentang tesis yang diajukan oleh Samuel P. Hungtinton, mereka berpendapat, bila saja Samuel P. Huntington mau jujur, maka semestinya ia kembali menulis. Yaitu menulis, untuk kemudian merefresh akan apa yang pernah menjadi tesisnya. Karena, prediksi dari Samuel P. Hutingtong, yakni tentang akan terjadinya benturan peradaban itu, nyatanya hingga saat ini tidak terjadi. Tesis yang dibuat tanpa ukuran waktu dalam proyeksinya itu dan sangat buming di tahun 1996-an itu, karena tesis tersebut selain unpredictable, juga tidak realiable. Paling tidak, buktinya adalah apa yang kita saksikan saat ini. Karena, tren yang muncul dalam percaturan global kini, justru telah menunjukkan begitu “mesra”-nya sub-sub peradaban dunia yang diproyeksikan akan mengalami benturan tersebut. Peradaban Islam maupun Konfusianisme, yang oleh Huntington dijadikan “sampling peradaban” untuk membenarkan tesisnya itu, justru saat ini secara substantif telah memperlihatkan fenomena sebaliknya. Style kedua peradaban itu, saat ini malah menjauh dari apa yang diprediksikan oleh Huntington. Antara peradaban Islam, Konfusianisme dan Barat serta peradaban lainnya, kini seolah-olah sedang ber-“bulan madu” di padang pasir dan di Great Wall. Bahkan, sudah menjadi political agreement di kalangan elit peradaban Barat untuk menjadikan Islam sebagai “the new counterpart”.
Perdebatan tentang hal itu (polemik tesia Hutington), adalah perdebatan tentang metodologi. Paling tidak, menyangkut persoalan kredibilitas refresentasif dari peradaban yang dijadikan sampling dari tesis Huntington, serta persoalan ukuran “kapabilitas klaim” dari sub-kelompok peradaban yang dijadikan objek tesisnya. Dan yang paling penting adalah persoalan determinant factor yang mempengaruhi style kebijakan dari sub-kelompok yang diklaim Huntington, mewakili “ordo” dari peradaban yang dijadikan samplingnya itu.
Pertama, persoalan kredibilitas refresentatif sampling. Pertanyaan “sederhana” yang dapat diajukan untuk menguji tesis Huntington adalah, apakah Islam dan Konfusianisme menguasai “rel” peradaban pada akhir abad 20? Bukankah sejak runtuhnya struktur internasional yang bipolar menjadi unipolar pada tahun 1990, hanya ada satu rel peradaban yang eksis. Dan itu, “Mbah”-nya adalah Barat. Islam dan Konfusianisme, sebagai sebuah entitas peradaban memang ada. Tetapi, dalam perspektif “the power behind the civilization”, kedua entitas tersebut tidaklah berbeda eksistensinya dengan entitas peradaban lainnya : wujuduhu ka adamihi.
Malah dalam beberapa hal, kedua entitas peradaban tersebut termodifikasi genre-nya oleh peradaban Barat. Sehingga, bila “Barat is Barat”, maka “Islam atau Konfusianisme is not all Islam atau Konfusianisme”.
Dalam posisi bargain yang demikian, apakah masih pas untuk menempatkan keduanya dalam posisi untuk saling dibenturkan (clashed)? Dalam konteks inilah, membangun tesis yang memprediksikan akan terjadi benturan peradaban, sesungguhnya adalah lebih pada upaya pembangunan political engineering untuk melakukan justifikasi atas kebijakan pre-emtive strike-nya dunia Barat. Dan itu terbukti.
Bila argumen tersebut, masih mengundang perdebatan soal apakah Islam/Konfusianime sudah dianggap punya kapabilitas atau tidak, dalam menempati “rel persaingan” peradaban sehingga tesis bahwa sesungguhnya hanya peradaban Barat yang dominatif, tidak benar, maka pertanyaan metodologis kedua dapat diajukan. Hingga kini, para pengamat internasional masih belum menemukan metode yang valid dan komprehensif, untuk menjawab tentang sub-kelompok manakah yang kapabel untuk diklaim bahwa mereka adalah pihak memiliki otoritas untuk menentukan arah dari peradaban yang melekat pada kelompoknya.
Kalau yang disorot oleh Huntington itu adalah para elit kelompok yang berkuasa dalam sebuah peradaban, maka menarik untuk dipertanyakan “apakah policy untuk mengarahkan peradaban itu terletak dalam genggaman kekuasaan mereka, atau justru sebaliknya”. Bicara peradaban yang ideal, seringkali berbenturan dengan kepentingan politik.
Lalu, elit politik manakah yang tidak care akan nasib kekuasaan yang ada dalam genggamannya? Mesir, Libya, Arab Saudi, Suriah, Iran, Indonesia, Malaysia ataukah Tiongkok (Cina)?
Kalau toh misalkan, ada elit politik yang “i don’t care about my popularity”, dan mati-matian dengan konsep peradaban yang idealnya, maka seberapa besarkah otoritas yang dimiliki para elit tersebut, untuk mengarahkan “arah” peradaban di tingkat grassroot. Di dalam negara Islam atau negara (penganut) Konfusianisme sekali pun, kerapkali para elit politik mereka mengalami keterbatasan kekuasaan bila sudah menyangkut ideologi (agama) warganya. Bahkan kini, dalam dunia dimana liberalisasi sudah menelusuk ke dalam ruang-ruang ideologis, apakah akan efektif, otoritas yang dimiliki oleh para elit tersebut? Dalam kaitan inilah, Samuel P. Huntington menurut pandangan penulis, ia mengalami kegagalan dan bahkan mengalami “krilulogi” untuk memahami falsafah kedua agama tersebut.
Ketiga, persoalan “determinat factor” yang mempengaruhi pembentukan style peradaban. Karena secara teoritis, wajah peradaban yang muncul, ditopang oleh postur dan style yang inheren dalam peradaban tersebut. Karena anatominya yang dinamis, maka wajah peradaban pun sangat dinamis pula. Kedinamisan itu terjadi seiring dengan determinant factor yang juga dinamis, tergantung pada orientasi apa yang mendasari “kebijakan luar negeri” peradabannya.
Wajah peradaban Islam atau Konfusianisme yang terbentuk di mata dunia saat ini, pada hakikatnya adalah akumulasi dari “kebijakan luar negeri” yang diambil oleh para elit kelompok yang ada dalam entitas peradaban tersebut. Karena kebijakan itu dimbil dari banyak pilihan, maka orientasi si elit mempengaruhi secara dominan. Oleh karena itu, sangat mungkin bila wajah peradaban Islam atau Konfusianisme yang kini muncul, bukanlah sebuah wajah peradaban yang ideal atau dikehendaki oleh semua yang yang ada di dalamnya. Apalagi, sudah menjadi pemahaman yang umum bahwa dalam suatu entitas peradaban, terdapat banyak mazhab atau sekte yang menjadi bagian dari kekuatan politik internalnya. Sebagai sebuah entitas, peradaban Islam atau Konfusianisme tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya (foreign determinant). Dan lingkungan yang dimaksud, tiada lain adalah peradaban Barat. Meski tidak semua, hampir sebagian besar warga dunia yang bukan berasal dari peradaban Barat, menganggap “sesuatu” yang berasal dari Barat adalah inovatif dan modern. Dalam ukuran dikotomik materil-sipirituil, peradaban Barat relatif lebih dominan menawarkan kesejahteraan materil, namun sesuatu yang “sangat gersang” bagi peradaban non Barat.
Thomas Hobbes meyakinkan para ilmuan sosial bahwa setiap orang secara alamiah cenderung mencari kesejahteraan materil yang dominan daripada kesejahteraan spirituil.
Karenanya, tidak heran bila kini telah terjadi “transmigrasi idiologis” dari sebagian anggota kelompok peradaban non barat ke peradaban Barat. Secara substanstif, fenomena perpindahan idiologis tersebut, merupakan perpindahan peradaban. Karena meski secara fisik, jasadnya ada di kelompok peradaban non Barat, namun sesungguhnya jiwanya telah ada di “Desa” peradaban Barat. Fenomena inilah yang penulis disebut sebagai “infiltrasi peradaban”.
Oleh karena itu, tesis Huntington tentang prediksi akan terjadinya benturan peradaban itu, tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi justru, akan lahir peradaban baru akibat proses “transmigrasi idiologis” yang terus-menerus, sebagai konsekuensi dari adanya kebijakn “open house” dari peradaban Barat. Ke depan, mungkin kita akan menyaksikan peradaban pasca Barat (post western civilization) atau peradaban Timur-Barat (east-western civilization).