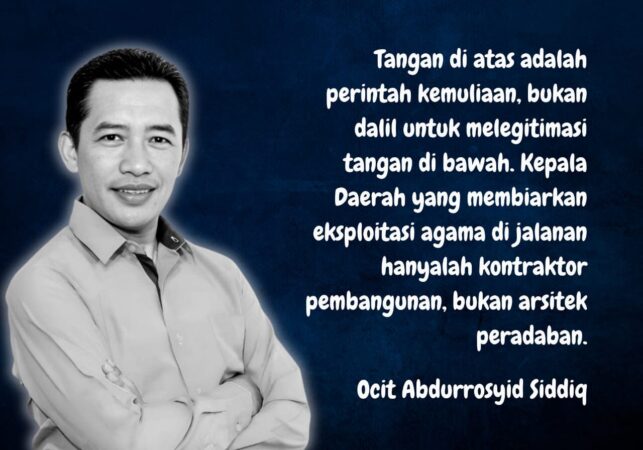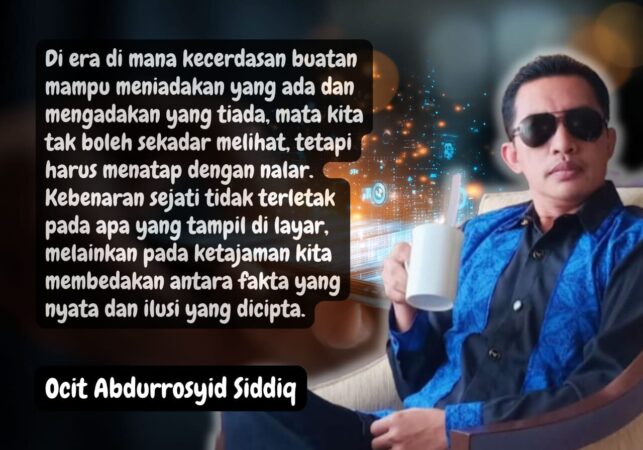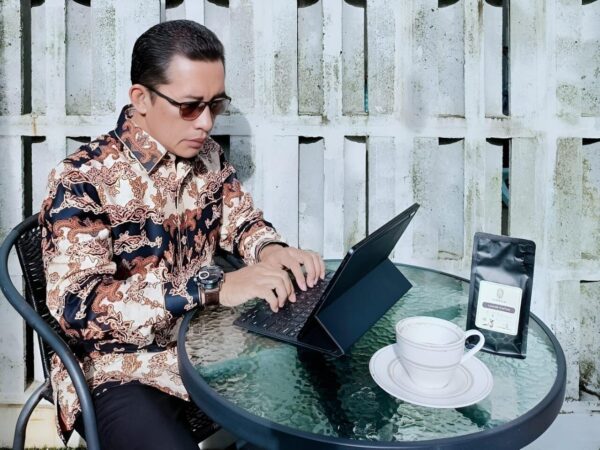Oleh : Dede Sudiarto, S.Pd.,M.M ( Bid.Pendidikan ICMI BANTEN )
Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membentuk mindset kerangka berpikir, nalar kritis, dan habitus belajar, bukan sekadar memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Indikator mutu belajar Indonesia menegaskan urgensi ini: pada PISA 2022, hanya sekitar 18% siswa Indonesia mencapai minimal Level 2 untuk matematika (kompetensi dasar bernalar kuantitatif), 25% untuk literasi membaca, dan 34% untuk sains; hampir tak ada yang menembus Level 5–6 (kategori top performers). Tren 2018–2022 juga memperlihatkan penurunan capaian, sementara kesenjangan performa justru menyempit karena penurunan pada kelompok berprestasi tinggi. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan “isi” pengetahuan tanpa pembentukan pola pikir dan kemandirian belajar akan sulit menutup defisit kompetensi dasar.
Dalam konteks “mengajar” sekaligus “mendidik”, disiplin, kejelasan aturan, dan konsistensi ekspektasi adalah elemen pedagodik yang tidak dapat ditawar. Di sinilah sebagian argumen untuk mempertahankan unsur-unsur gaya otoriter dalam makna pedagogik yang terdefinisi (struktur kuat, aturan jelas, konsistensi) muncul sebagai local treatment yang adaptif terhadap kondisi SDM dan ekosistem sekolah yang masih berjuang mengejar kompetensi dasar. Namun, bukti empirik terbaru perlu dihadirkan agar penerapannya tidak berubah menjadi praktik koersif. Studi Paediatrica Indonesiana (2025) pada remaja sekolah di Jakarta Utara menemukan bahwa pola asuh otoriter berkorelasi positif dengan masalah perilaku dan relasi sebaya; artinya, kontrol yang keras cenderung meningkatkan risiko problem perilaku bila tidak diimbangi keterlibatan emosional dan dialog. Temuan ini memperkuat literatur bahwa otoriter murni (kontrol tinggi, kehangatan rendah) berdampak kurang menguntungkan dibanding otoritatif (kontrol terstruktur + kehangatan/rasionalitas).
Di tingkat ekosistem, Indonesia menunjukkan kemajuan kapasitas manusia: IPM 2024 mencapai 75,02 (kategori tinggi) dan meningkat 0,85% dibanding 2023. Namun, akselerasi kualitas belajar masih tertahan; bahkan PISA mencatat beban ketahanan sekolah dan kesiapan pembelajaran jarak jauh masih terbatas. Dengan kata lain, kemajuan “stok” SDM umum belum otomatis terkonversi menjadi “arus” kompetensi literasi-numerasi siswa. Ini menegaskan bahwa strategi pendidikan harus menyentuh kultur kelas dan keluarga, bukan semata kurikulum.
Karena itu, bila “gaya otoriter” hendak dipertahankan sebagai budaya perlakuan lokal, ia harus direkalibrasi menjadi disiplin suportif: struktur dan ketegasan (kejelasan aturan, konsekuensi konsisten, target belajar terukur) digabungkan dengan kompetensi sosial-emosional pendidik (empati, umpan balik dialogis, penjelasan rasional atas aturan). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip otoritatif dan lebih aman secara psikososial. Perlu diingat, praktik kekerasan fisik/emosional yang sayangnya masih lazim dilaporkan di sekolah, bukan bagian dari disiplin edukatif dan berisiko memperburuk iklim belajar. UNICEF mencatat perundungan dan shaming masih umum, dengan 18% siswi dan 24% siswa terdampak; guru juga dilaporkan kerap menggunakan hukuman fisik/emosional. Reformasi budaya disiplin karenanya harus menolak kekerasan sekaligus menjaga ketegasan.
Secara kebijakan, pijakan legal dan normatif juga menuntut perbaikan. Larangan eksplisit hukuman fisik di rumah dan sekolah belum sepenuhnya terjamin dalam peraturan perundang-undangan, sehingga “otoriter edukatif” berisiko disalahartikan menjadi hukuman fisik/psikis. Laporan negara (Februari 2024) dari Global Partnership to End Violence Against Children menandai Indonesia masih memerlukan pelarangan tegas hukuman fisik di berbagai setting. Ini penting agar disiplin berbasis struktur tidak menyimpang menjadi kekerasan yang kontraproduktif terhadap capaian belajar dan kesejahteraan siswa.
Dengan membaca data mutakhir, rekomendasi praksisnya adalah: (1) utamakan pengembangan pola pikir (berpikir kritis, regulasi diri, resiliensi) melalui target kompetensi yang jelas dan latihan bernalar; (2) ajarkan sambil mendidik: setiap pengajaran konten harus diiringi pembiasaan nilai (tanggung jawab, growth mindset, etos kerja); (3) terapkan disiplin suportif, struktur ketat tanpa kekerasan, transparansi konsekuensi, dan komunikasi dua arah; (4) perkuat literasi pedagogis guru dan orang tua agar “ketegasan” tidak berubah menjadi hukuman fisik/psikis; (5) sinkronkan kebijakan: dorong regulasi yang menegaskan pelarangan kekerasan sekaligus melatih strategi manajemen kelas yang tegas-empatik. Dengan demikian, elemen ketegasan yang selama ini diasosiasikan dengan otoriter dapat diakomodasi sebagai instrumen budaya lokal yang terarah, selaras bukti ilmiah, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi, bukan sekadar kepatuhan.