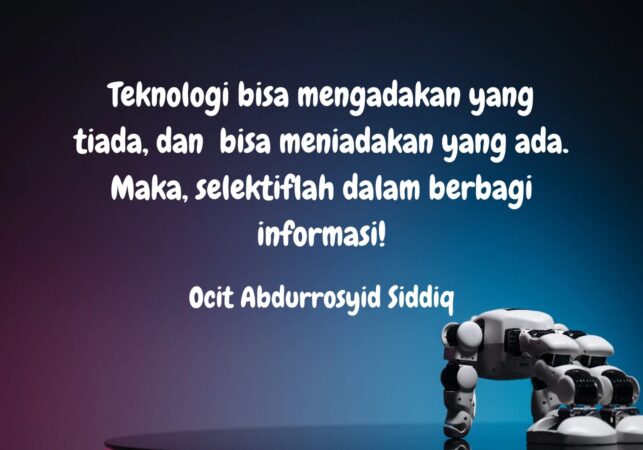Ocit Abdurrosyid Siddiq
Dunia hari ini terasa bergerak lebih cepat dari detak jantung kita sendiri. Perkembangan teknologi, yang semula diciptakan sebagai pelayan peradaban, kini tumbuh menjadi raksasa yang seolah-olah meninggalkan penemu dan penciptanya di belakang. Kita telah berpindah dari masa di mana informasi adalah barang mewah yang harus ditunggu dari mesin cetak koran, menuju era di mana informasi tumpah ruah seperti air bah, menekan kita dari segala sisi melalui layar kecil di genggaman tangan. Namun, di balik kecanggihan yang mampu “mengadakan yang tidak ada dan meniadakan yang ada” ini, tersimpan sebuah ironi yang menyayat: kita semakin pintar menciptakan alat, namun semakin abai dalam menggunakannya dengan bijak.
Gawai dan internet telah mengubah lanskap kognitif kita. Dahulu, berita adalah hasil dari proses kurasi yang panjang. Sekarang, setiap orang adalah penerbit, setiap jempol adalah redaktur. Kecepatan telah menggantikan ketepatan. Dalam hiruk-pikuk ini, batasan antara kenyataan dan rekayasa menjadi kabur. Sesuatu yang palsu bisa tampak lebih meyakinkan daripada kebenaran, asalkan ia dikemas dengan warna yang mencolok atau narasi yang menyentuh emosi. Di sinilah letak ujian terbesar kita sebagai manusia modern: kemampuan untuk selektif dan memilah di tengah belantara digital yang menyesatkan.
Fenomena yang paling mengusik batin belakangan ini adalah betapa mudahnya orang-orang membagikan informasi secara serampangan. Gejala ini tampak sangat nyata pada segmen masyarakat yang belum sepenuhnya “melek” teknologi, terutama dari kalangan generasi baby boomer. Tentu, ini bukan generalisasi yang bermaksud merendahkan, namun merupakan sebuah potret sosiologis yang perlu direnungkan. Bagi mereka yang tumbuh besar dalam suasana komunikasi tatap muka atau media satu arah yang terpercaya, ledakan informasi digital adalah rimba yang asing. Sayangnya, kemauan untuk belajar memahami mekanisme teknologi ini seringkali masih rendah, kalah oleh rasa nyaman pada kebiasaan lama.
Di segmen inilah muncul perilaku yang mengkhawatirkan. Seolah-olah setiap pesan yang masuk ke dalam grup percakapan atau linimasa media sosial adalah sebuah kebenaran mutlak yang turun dari langit. Ada sebuah kecenderungan psikologis yang kuat: informasi tidak lagi dinilai berdasarkan validitas datanya, melainkan berdasarkan “rasa pas” atau kecocokan isinya dengan keyakinan pribadi. Jika sebuah berita—betapapun absurdnya—selaras dengan kebencian atau ketidaksukaan mereka terhadap sesuatu, maka tanpa berpikir panjang, jari akan langsung menekan tombol share.
Kita sering melihat pola yang serupa. Informasi tersebut biasanya berkisar pada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan, narasi tentang keberpihakan pada pihak asing dalam urusan bisnis, hingga teori konspirasi yang menyulut rasa takut. Bagi mereka, informasi tersebut bukan sekadar berita, melainkan amunisi untuk membenarkan prasangka. Kebenaran objektif menjadi nomor sekian, sementara kepuasan emosional karena merasa “benar” menjadi prioritas utama.
Tragedi yang sebenarnya terjadi ketika fakta yang sesungguhnya disodorkan di depan mata. Alih-alih menerima dengan lapang dada, seringkali muncul sikap ketidakberterimaan yang keras. Ada semacam luka ego ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa apa yang mereka percayai adalah salah. Rasa kecewa ini tidak lantas membuat mereka berhenti; sebaliknya, tanpa rasa bersalah, mereka justru memproduksi atau menyebarkan hoaks baru dengan tema yang berbeda. Ini adalah lingkaran setan yang dipicu oleh ketidakmampuan untuk mengakui kekhilafan. Kebohongan demi kebohongan ditumpuk demi menutupi rasa malu karena telah tertipu sebelumnya.
Akar dari semua ini, jika kita renungkan lebih dalam, adalah rendahnya literasi. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan, namun membenci kedalaman. Kurangnya minat baca menjadi lubang hitam yang menghisap akal sehat. Saat disajikan sebuah artikel fakta yang mendalam dengan penjelasan yang panjang lebar, keluhan yang muncul selalu sama: “Panjang amat, capek bacanya.” Masyarakat kita semakin haus akan sesuatu yang ringkas, padat, dan instan. Mereka lebih menyukai slogan yang provokatif dan jargon yang membakar semangat daripada data statistik yang membosankan namun akurat. Kita telah menjadi masyarakat “judul”, di mana keputusan diambil hanya dengan membaca kepala berita tanpa menyentuh isi.
Kondisi ini diperparah oleh adanya “ruang gema” (echo chamber). Orang-orang dengan karakter dan prasangka yang sama berkumpul, saling menguatkan, dan saling membumbui cerita palsu tersebut hingga terasa seperti kebenaran kolektif. Padahal, apa yang mereka bangun dan dukung sejatinya hanyalah sebuah kubangan kebohongan. Di dalam kubangan itu, mereka merasa aman, padahal perlahan-lahan mereka tenggelam dalam ketidaktahuan yang berbahaya. Mereka merasa sedang memperjuangkan kebenaran, padahal mereka hanya sedang menjadi pion bagi kepentingan pihak-pihak yang mengambil untung dari perpecahan.
Di penghujung perenungan ini, mari kita menarik napas sejenak dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian yang dipicu oleh berita palsu? Bukankah energi kita terlalu berharga jika hanya digunakan untuk memaki-maki situasi yang tidak kita pahami sepenuhnya?
Marilah kita mulai lebih selektif dalam berbagi informasi. Sebelum jempol bergerak untuk menyebarkan sesuatu, tanyakanlah pada nurani: Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini hanya akan menambah kegaduhan yang sia-sia? Kita perlu melatih diri untuk tidak mudah terprovokasi. Kebenaran tidak memerlukan sumpah serapah atau caci maki untuk tegak. Sebaliknya, kebohonganlah yang seringkali membutuhkan suara keras agar terdengar meyakinkan.
Mari kita kurangi kebiasaan menyalahkan orang lain, menyalahkan sistem, atau menyalahkan keadaan tanpa dasar yang kuat. Alangkah lebih indahnya jika sisa waktu dan energi yang kita miliki digunakan untuk memperbanyak kebaikan yang bernilai pahala. Di usia yang semakin senja bagi sebagian kita, atau di tengah dunia yang semakin renta ini, bekal yang paling nyata untuk kehidupan kelak bukanlah kemenangan dalam debat kusir di media sosial, melainkan ketenangan hati dan amal jariah yang kita tanam.
Biarlah perkara-perkara “duniawi” yang rumit, urusan politik yang penuh intrik, dan perdebatan teknologi yang tak berujung itu menjadi porsi bagi anak-anak muda generasi berikutnya. Mereka lahir di zaman ini, mereka memiliki perangkat mental yang berbeda untuk menghadapinya. Tugas kita adalah memberikan teladan tentang kebijaksanaan, bukan malah menambah beban sejarah dengan warisan hoaks dan perpecahan.
Dunia akan terus berputar dengan segala kecanggihannya. Kita mungkin tidak bisa mengejar kecepatannya, namun kita selalu bisa memilih untuk tetap tegak di atas landasan etika dan kejujuran. Mari kembali ke literasi yang sesungguhnya: membaca dengan hati, mencerna dengan logika, dan berbicara dengan cinta. Semoga sisa perjalanan kita di dunia ini lebih dipenuhi dengan kedamaian, sehingga saat tiba waktunya nanti, kita melangkah dengan ringan tanpa memikul beban kebohongan yang pernah kita sebarkan.
*
Tangerang, Selasa, 6 Januari 22026
Penulis adalah pengurus ICMI Orwil Banten, Ketua Bidang Kaderisasi PB. Mathlaul Anwar