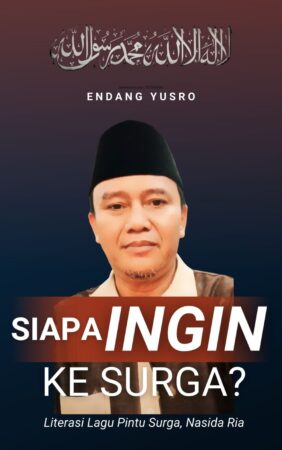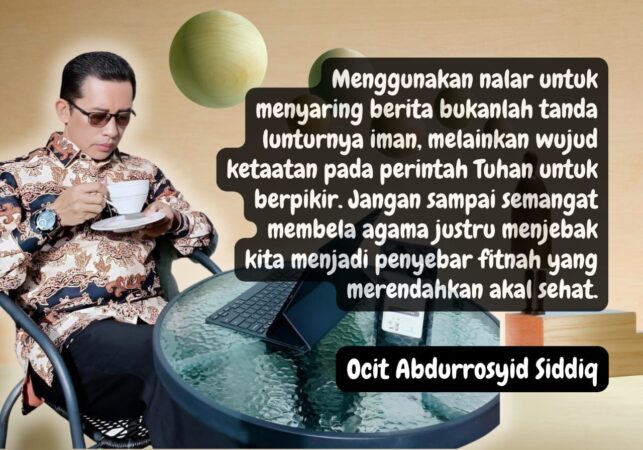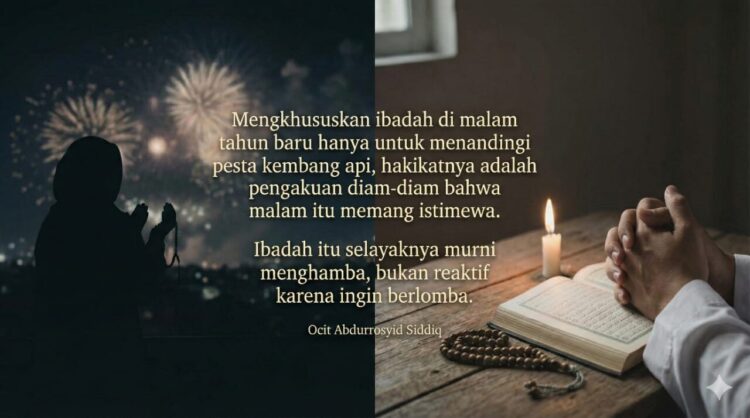Oleh : Adung Abdul Haris
I. Pendahuluan
Kata hegemoni berasal dari bahasa Yunani, “hegemonia” yang berarti pemimpin. Jadi, sama halnya dengan sifat umum yang terkait dengan pemimpin, maka hegemoni memiliki kata kunci “pengaruh” dan “otoritas”. Konsep hegemoni itu mula-mula diperkenalkan oleh Antonio Gramsci (intelektual Perancis). Menurut Gramsci, hegemoni adalah kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa (kelas penguasa). Menurut Gramsci, bahwa unsur esensial yang paling banyak mengenai filsafat modern tentang praksis (terkait dengan pemikiran dan tindakan) adalah konsep filsafat sejarah “hegemoni”. Gramsci menolak gagasan perkembangan sejarah yang bersifat determinis atau “yang pasti terjadi”. Sementara hegemoni menunjuk pada suatu kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara lain. Dalam konteks politik internasional misalnya, pada periode perang dingin, bahwa pertarungan-pertarungan antara negara adikuasa, seperti Amerika Serkat dengan bekas Uni Sovyet (Rusia sekarang), saat itu disebut sebagai perang untuk merebut kekuatan hegemonik dunia. Gramsci membedakan antara hegemoni dengan kekuatan (force). Jika kekuatan meliputi penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat suatu cara produksi tertentu, sedangkan hegemoni adalah mencakup perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif” dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas kekuasaan melalui penggunaan kepemimpinan intelektual, moral dan politik.
Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Muchtar Pabotinggi (peneliti LIPI). Menurutnya, hegemoni Barat saat ini, tekanannya pada dominasi ideologis/politis atas kaidah-kaidah moral dan intelektual yang berlaku, yitu hegemoni melalui upaya produk-produknya, menjadi penentu satu-satunya dari apa yang dipandang benar secara moral maupun intelektual. Hegemoni adalah dominasi sosial dimana “arah lain atau pendapat lain kerapkali dilenyapkan dari wacana diskusi, dan bahkan diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak ada”.
Menurut Muchtar Pabotinggi, superaioritas Barat atas segala sesuatu yang “bukan Barat” saat ini merupakan pesan tunggal. Sementara salah satu menifestasi terkuat dari hegemoni kultural-ideologis itu adalah diskursus Barat yang disebut dengan “orientalisme”. Sedangkan strategi orientalisme tergantung secara konstan pada superioritas Barat yang dapat diwujudkan dalam berbagai posisi yang selamanya menempatkan superioritas Barat atas Timur.
II. Pandangan Para Akademisi Timur Tengah Soal “Hegemoni Barat”
Dalam pandangan para pengamat dan para akademisi (studi Timur Tengah), mereka melihat bahwa kebanyakan orientalis Barat memang selalu berprasangka negatif terhadap Timur (Islam). Kemudian muncul sebuah pertanyaan, seriuskah prasangka seperti itu? Apakah pengaruhnya terhadap mereka yang mengajar (studi tentang Timur Tengah) saat ini? Jawaban pertanyaan tersebut telah kemukakan oleh Edward W. Said dalam karyanya yang berjudul, “Orientalism”. Menurut Edward Said, “studi ketimuran” sebagai disiplin keilmuan secara material dan intelektual terkait dengan ambisi politik dan ekonomi Eropa, dan orientalisme telah menghasilkan “gaya pemikiran yang didasarkan pada perbedaan teologis dan epistemologis antara “Timur” dan “Barat” dalam banyak hal. Edward Said menjelaskan, bahwa orientalisme Barat mengembangkan cara-cara “pembahasan” tentang Islam (khusunya Arab) sehingga menyempurnakan rasa superioritas budaya Barat atas budaya lain. Edward Said juga melihat adanya bias dalam tulisan-tulisan para kolonialisme, misionaris, dan sarjana Barat. Bias yang paling populer menurut Edward Said adalah proyeksi media tentang Arab saat ini, yang dikomotasikan sebagai masyarakat yang terbelakang, irasional dan lain sebagainya.
Pencitraan (citra negatif) yang dibangun oleh Barat dalam konteks menilai dunia Timur sudah sedemikian kuatnya, sehingga Barat dikonotasikan sebagai kemajuan, desentralisasi dan superioritas. Sementara Timur diidentikan dengan stagnasi, sentralisasi, kekacauan dan seterusnya.
Sementara kondisi yang mencerminkan dunia pasca runtuhnya komunis adalah dominasi dan hegemoni Barat dalam ruang lingkup ekonomi dan politik yang didasarkan pada tiga prinsip yang fundamental, yaitu: Pertama, kapitalisme dan ekonomi pasar. Kedua, hak-hak asasi manusia dan demokrasi sekular-liberal. Ketiga, negara kebangsaan sebagai kerangka dasar bagi hubungan Internasional. Oleh karena itu, menurut Edwar Said, agar munculnya sebuah ideologi di dunia ketiga, yang berani menentang nilai-nilai Barat. Sementara jalan ideologi yang akan muncul untuk melawan Barat tergantung pada tipe para pemimpin yang muncul sebagai pembela kepentingan negara. Edward Said, ia menempatkan Cina, India, Iran, Mesir, Rusia (termasuk Indonesia, Brazil dan Afrika Selatan) di bagian depan daftar negara yang dipastikan memainkan peran penting dalam perjuangan ideologi melawan hegemoni Barat.
Bahkan, dikotomi Barat-Islam dewasa ini mencuat kembali, karena hasil persepsi yang timbul dari Pembagian dunia pasca perang dingin ke dalam Timur dan Barat. Dalam pencariannya terhadap lawan baru sejak akhir tahun 1980-an, Barat telah memilih untuk melawan Islam, yaitu dengan mengangkat kembali isu-isu budaya sebagai pemicu konflik. Menurut Prof. Dr. Arkoun dan Munoz, menguatnya persepsi dikotomis Barat-Islam karena adanya interpretasi historis yang didasarkan pada prinsip ideologi antagonisme (misalnya : Bizantium vs kekaisaran Islam, Kerajaan Kristen vs Andalusia, Turki Usmani vs Eropa, Nasionalisme Arab-Islam vs Barat dan seterusny). Persaingan hegemoni politik dan ekonomi antara dunia Kristen abad pertengahan dan kekaisaran Arab-Islam menjadi sebuah konfrontasi antar peradaban, yang menyebabkan kesadaran Barat memahami Islam sebagai lawan. Sementara Kristen dan Yudaisme terintegrasi dengan Barat ke dalam peradaban Yudeo-Kristen, sedangkan Islam terpinggirkan. Berbagai prasangka yang diciptakan oleh konfrontasi Islam dan Kristen di Spanyol dalam perang Salib atau perang melawan Turki terus merasuki kesadaran Barat secara mendalam. Maka oleh Munoz, hal itu disebut sebagai “Kesalahan Penafsiran Sejarah”. Secara metodologis memang ada kecenderungan yang salah di kalangan peneliti dan analis yang mengukuhkan ideal-ideal Barat sebagai satu-satunya patokan dan menempatkannya secara berbeda dengan ideal-ideal Islam. Kecenderungan itu akhirnya mengimplikasikan pada penyederhanaan atas perkembangan politik dan sosial di dunia Islam dan pemikiran sebagai tanda-tanda religiusitas yang ekstrem.
Sekedar contoh, Revolusi Islam Iran misalnya, hal itu disebut-sebut oleh Barat sebagai sebuah ungkapan fanatik dari cita rasa keagamaan, dengan terus mengabaikan semua faktor sosial, politik dan ekonomi yang menimbulkan gerakan revolusioner itu. Untuk alasan yang sama, bahwa fenomena revolusi Islam Iran itu oleh dunia Barat hanya direduksi menjadi pemaksaan keagamaan yang tidak rasional dan juga tidak mempertimbangkan mengapa revolusi Iran itu muncul?
Sementara terorisme dan perang saudara, ketika melibatkan kaum Muslimin cenderung dijelaskan sebagai konsekuensi Islam itu sendiri (yang melekat dengan ajaran jihad-nya), bukan akibat dari ketidak adilan global (ketidak-adilan sosial, ekonomi dan politik). Dalam pandangan fundamentalis Muslim, Amerika jauh lebih bengis daripada Uni Soviet (Rusia), karena pengaruh budaya dan ekonomi Amerika memang melampaui Uni Soviet. Demikian pula, pasca Perang Dingin (Cold War), Amerika juga menganggap ideologi kelompok fundamentalis Muslim merupakan tantangan yang jauh membahayakan. Pendeknya, Amerika harus menghadapi rintangan yang lebih besar di bawah kelompok fundamentalis. Sementara dalam pandangan fundamentalis Muslim, Amerika dan sekutu-sekutunya, memang memiliki pengaruh budaya yang kuat. Misalnya, bahasa, gaya hidup, media massa (program televisi, musik, video game, komik, teks buku dan seterusnya). Di wilayah agama misalnya, Amerika mengeksport dua hal : Kristen (sebagai saingan Islam tradisional) dan sekularisme (sebagai saingan modern). Missionaris Kristen merupakan bayang-bayang besar menurut pandangan fundamentalis Muslim.
Sementara Perang Dingin (Cold War) sudah dianggap kenangan, namun kenyataannya Amerika masih menghadapi risiko tinggi yang mereka sebut dengan “Green Peril”. Green atau Hijau dikonotasikan sebagai warna Islam, sementara “Peril” disimbolkan sebagai fundamentalis Muslim Timur Tengah. Fundamentalis Muslim itu dianggap sebagai gerakan revolusi agresif, militan, dan garang sebagaimana Bolshevik, Fasis dan Nazi yang anti demokrasi, anti-sekuler, otoriter dan segala macam stigma buruk lainnya. Itulah Perang Dingin Baru (The New Cold War) yang disebut oleh Jurgensmeyer “The New Cold War: Religious Nationalism Confront the Scular State, University of California Press”. Demikian juga menurut Leon T. Hadar, “Policy Analysis, The “Green Peril” (Menciptakan Ancaman Fundamentalis Islam).
Memang tidak mudah untuk menunjuk siapa yang mulai membangun citra antagonisme itu (antagonis Barat dan Timur). Karena, di satu sisi sebagian kaum Muslimin memandang Barat sebagai koloni yang harus dilawan, dan sebaliknya, Barat memandang kaum Muslimin sebagai ancaman yang harus dihegemoni. Bahkan Bernard Lewis berpendapat, mengapa muncul kelompok-kelompok Islam yang anti Amerika atau anti Barat? Padahal menurut Bernard Lewis, jika alasan mereka adalah karena persoalan kolonialisme dan imperialisme, maka tidaklah tepat, karena Amerika sendiri tidak pernah menjajah negeri Muslim. Seharusya yang paling anti terhadap Amerika itu menurut Bernard Lewis adalah Vietnam dan Kuba, yang memang realitasnya kedua negara itu pernah diinvansi (dijajah) oleh Amerika.
Namun, alasan Bernanrd Lewis itu terkesan terlalu naif, karena ia hanya melihat penjajahan dalam bentuk fisik saja, dan cenderung hanya cukup dengan meminta maaf. Padahal faktanya sudah jelas, karena apa yang dilakukan oleh Amerika dan para sekutunya (negera Barat) dalam menghegemoni Irak misalnya, sudah sangat mencolok. Bahkan, menurut pendapat para pengamat politik Timur Tengah, dan salah satunya menurut Riza Syihbudi, bahwa tudingan Amerika terhadap kelompok garis keras (Islam) sebagai teroris kerapkali terjadi, alias selalu berulang-ulang. Kalau ada kekerasan dan teror selalu dikaitkan dengan orang-orang Arab, Timur Tengah dan Islam. Persoalan itu sudah menjadi opini publik yang dibangun melalui penguasaan media massa oleh kelompok tertentu. Bahkan kualitasnya kini sudah meluas ke Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hegemoni Barat terhadap Islam di Timur memang sudah sedemikian kuatnya, sehingga memasuki relung-relung kehidupan: ekonomi, politik, budaya dan agama. Bahkan menurut Riza Syihbudi, bahwa tidak ada wilayah budaya yang mencemaskan mengenai ancaman penetrasi budaya dan peradaban. Sementara simbol sentral kegelisahan bagi dunia Barat (Amerika) ialah Islam dengan otentisitas dan identitasnya. Bahkan, dalam konteks hubungan antara peristiwa musibah kemanusiaan di WTC, AS misalnya, tidak tepat jika Islam selalu dikait-kaitkan dengan teror dan kekerasan. Namun seyogyanya, permasalahan itu harus dilihat secara makro dalam konstalasi politik global dan khususnya oleh Amerika yang memang dikenal sebagai negara adidaya yang penuh arogansi itu.
III. Dikotomi Barat Dan Timur Harus Dipersempit
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (alm), Azyumardi Azra, ketika masih hidup ia pernah menegaskan, bahwa dikotomi antara Barat dan Timur itu harus terus dipersempit. Karena menurutnya, tidak semua hal yang berasal dari Barat itu negatif, tetapi ada hal-hal yang positif sekaligus dapat membawa kemajuan bagi umat Islam. Azyumardi Azra menyampaikan hal itu pada acara seminar Internasional yang bertemakan “Islam dan Tantangan Globalisasi”. Seminar tersebut berlangsung di Yogyakata, Sabtu (Republika, 15/3/2014). Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII). Seminar tersebut dihadiri oleh peserta dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Perancis, dan Iran. Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra, bahwa umat Islam membutuhkan Barat, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena, dalam Alquran sudah disebutkan tidak ada perbedaan antara Timur dan Barat. “Mana yang positif dari Barat kita ambil, dan mana yang negatif dan termasuk yang ada di internal umat muslim sendiri harus kita tinggalkan. Misalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa maju kalau kita hidup dalam kerukunan dan aman,” kata Azyumardi. Lebih dari itu Prof. Dr. Azyumardi sangat menyanyangkan, karena masih adanya perang yang tidak henti-hentinya, yakni yang terjadi di negara-negara Muslim seperti Asia Selatan, India, Pakistan, Iran, Afganistan, Syiria, dan Bangladesh. Setiap hari di negara tersebut terjadi bom yang membuat warga merasa tidak aman. “Kalau perang terus-terusan, lalu kapan kita (umat Islam) membangunnya, kapan memajukan Iptek. Karena itu hal yang negatif dan bersifat seketarian yang berlebihan, tindakan militeristik yang berlebihan, penggunaan kekerasan, penggunaan alat yang mematikan seperti bom dan lain sebagainya harus ditinggalkan,” katanya. Lebih dari itu menurut Azyumardi Azra, memang ada pendapat, bahwa orang Barat sangat bebas dalam seks. Tetapi tidak semua orang Barat melakukan seks bebas. “Kita jangan menggeneralisasi semua orang Barat jelek. Apalagi di Barat juga banyak orang Muslim,” ujarnya. Orang Muslim di Barat, kata Azyumardi, telah menegakkan ajaran Islam yang mengajarkan kehidupan keluarga yang baik yaitu pernikahan yang baik terhadap orang Barat. “Itu yang kita ikuti,” katanya. Namun Azyumardi Azra merasa optimistis, bahwa dikotomi antara Barat dan Timur itu akan terus mengecil (semakin menyempit), dan kalau itu bisa terjadi maka akan muncul kedamaian. Bahkan umat Islam bisa hidup lebih maju karena orang Islam akan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melihat asalnya dari Barat atau negara mana.
Selain itu, Azyumardi juga meperingatkan kepada umat Islam agar tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Selama ini ada kritikan jika orang Barat konsumtif. Namun umat Islam juga tidak kalah konsumtifnya, terutama negara-negara Arab yang kaya. “Mereka memiliki uang bukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin di negara-negara muslim Eropa atau di mana saja. Namun digunakan untuk membeli klub sepakbola Eropa yang harganya mahal,” tandasnya. Oleh karena itu, Azyumardi menyarankan kepada negara Arab yang kaya agar tidak menghambur-hamburkan sumber daya. “Sumber daya minyak atau apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada kita, seyogyanya digunakan secara bijak dan cerdas, serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam,” katanya.
Sementara Rektor UII Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan sebetulnya umat Islam yang menjadi minoritas di Barat, tentunya bisa hidup berdampingan dengan mayoritas non muslim. Seperti hasil penelitian terhadap dinamika kehidupan komunitas muslim Kampung Jawa di Bangkok baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan. Dalam bidang kehidupan sosial keagamaan, kata Edy, komunitas muslim Kampung Jawa mempunyai kebebasan dalam menjalani ritual keagamaan. Keberadaan masjid Jawa yang masih berdiri kokoh menandakan komunitas tersebut didukung oleh pihak pemerintah maupun lingkungan sekitar.
IV. Filosofi Dalam Konsep Budaya Barat Dan Timur
Secara kudroti, manusia mempunyai kecenderungan untuk mendefinisikan identitasnya. Hal itu dilakukan dengan menciptakan atau menampilkan ciri-ciri penting sebagai pembeda dengan komunitas manusia lainnya. Karena kesamaan itulah, maka mereka dapat difahami sebagai kesatuan yang saling mengikat. Kecenderungan itu, berkaitan dengan konsep keberbedaan (yang berbeda). Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh seorang sosiolog (Otherness). Otherness menjelaskan, rasa ketidaksesuaian, ketidakpatuhan, dan ketidakterkaitan seseorang terhadap lingkungannya. Maka sama seperti identitas, konsep keberbedaan itu juga lahir dari proses persetujuan, ketidaksetujuan, atau negosiasi yang terjadi diantara manusia. Dari negosiasi atas identitas, konsep, dan preferensi itu, maka muncullah variasi di dalam masyarakat. Sementara dalam kasus Timur dan Barat misalnya, hal itu terbentuk sebuah struktur dikotomis (yang terbagi dua).
Sedangkan salah satu pemahaman tentang dunia Barat dan Timur itu sendiri pertama kali muncul, yaitu setelah perjalanan Christopher Columbus pada tahun 1492, yaitu menuju timur jauh. Dalam perjalanan itu, ia akhirnya menemukan kawasan yang ia sebut sebagai dunia baru. Kawasan itu disebut Dunia Baru untuk membedakannya dengan kawasan asal Chirstopher Columbus yang dianggap lebih tua dan lebih dulu berkembang, yaitu dikenal sebagai Dunia Lama (dunia lama). Perjalanan dan pengenalan yang dilakukan oleh Chirstopher Columbus. Sementara perjalanan itu disebut “Pertukaran Kolumbia”, karena terjadinya pertukaran komponen-komponen kehidupan antara dunia lama (negara-negara barat) dan dunia baru (negara-negara timur). Sementara beberapa hal yang dipertukarkan antara lain adalah gagasan dan pemikiran, produk-produk seperti makanan, keberagaman penduduk, dan penyakit. Sebagai usaha untuk membedakan keduanya, maka pihak yang menjalani pertukaran, akhirnya kedua tempat itu membagi dunia menjadi dua belahan (hemisfer); belahan bumi barat (belahan barat) dan belahan bumi timur (belahan timur). Sedangkan belahan dunia barat terdiri dari benua Amerika dan Eropa, sementara belahan timur terdiri dari benua Afrika, Australia, dan Asia.
A. Mengapa Bisa Ada Sentimen Khusus Dalam Konsep Barat Dan Timur
Sesungguhnya, pemberian lebilitas atau identitas itu dimaksudkan agar kita dapat mengenal atau membedakan satu hal dengan yang lainnya dengan lebih mudah. Akan tetapi, proses lebelitas (identifikasi) itu kemudian mempengaruhi terbentuknya persepsi-persepsi tertentu hingga saat ini. Dan persepsi itulah yang terus menciptakan rasa, keingintahuan, dan ketertarikan emosional. Dan perasaan-perasaan itulah yang juga dikenal sebagai sentimentil antara Barat dan Timur.
Sentimen itu sendiri dapat berbentuk positif, negatif, atau netral. Sedangkan sifat suatu sentimen, hal itu bergantung pada apa yang membentuk dan mempengaruhi persepsi sang pemilik sentimen itu. Dalam konteks ini, sentimen yang muncul pada konsep barat dan timur, yaitu berkembang dari percampuran antara kepercayaan dan perasaan yang kemudian diwujudkan dalam tindakan. Sementara berkaitan dengan “Columbian Exchange”, jika dilihat dari sisi ekonomi, sentimen terhadap belahan dunia barat tampak saat ini yang dikonotasikan (relatif) positif, yaitu mengalami kemajuan dari berbagai dimensi. Hal itu karena pertukaran antara timur dan barat memungkinkan datangnya keuntungan bagi kedua belahan dunia.
Sementara terbentuknya kedua belahan dunia yang dianggap saling bertolak belakang itu didorong oleh hasrat primordial (untuk berkelompok dengan yang sejenis) dan esensial (tidak terhindarkan). Contohnya, belahan dunia barat, terutama di zaman kolonial dulu memang terus memperkenalkan sejumlah bibit tanaman yang tidak ditemukan di dunia baru (dunia timur), seperti kentang, ubi, jagung, singkong. Selain itu, ada juga tanaman lainnya seperti gula, kopi, tomat, cabai, coklat, kacang, dan nanas. Tanaman-tanaman itu pun akhirnya terus memperkaya cita rasa masyarakat di dunia timur. Bahkan beberapa diantaranya kini menjadi bahan utama makanan khas negaranya.
Di sisi lain, dunia timur juga terus memperkenalkan tembakau dan rempah-rempah ke dunia barst (Eropa dan Amerika). Bahkan tembakau dan rempah-rempah itu sempat menguasai perdagangan dunia dan menjadi komoditas berharga, bersama dengan komoditas unik dan eksotis lainnya, yang berasal dari belahan timur.
Namun, jika dilihat dari sisi kebertahanan hidup manusia, pertukaran itu ternyata sangat berisiko. Karena, kedatangan dari dunia lama (barat) kerapkali membawa sejumlah penyakit yang sebelumnya tidak dikenal dan tidak dapat diobati oleh masyarakat di timur. Karena pertukaran itu, wabah penyakit seperti cacar, demam tifoid, kolera, dan tipes pun sempat menyerang dunia baru (timur). Sebaliknya, mereka yang kembali ke negara-negara dunia lama (barat) juga tidak jarang akhirnya pulang dengan membawa penyakit malaria dan sifilis. Dua contoh tersebut telah menunjukkan bahwa satu peristiwa dapat menimbulkan konsekuensi dan aksi yang berbeda-beda. Dari konsekuensi itulah, maka lahirlah berbagai sentimen barat dan timur yang kita kenal hingga sekarang ini.
B. Apa Pengaruh Konsep Barat Dan Timur Terhadap Kehidupan Masyarakat Masa Kini?
Jika kita memahami konsep barat dan timur secara positif, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dunia telah saling mengenal dan mampu beradaptasi dengan baik. Kemampuan itu tentu saja sangat berguna dalam proses globalisasi. Globalisasi sendiri sering dianggap sebagai proses penyeragaman selera, rasa, preferensi, hingga identitas. Padahal, globalisasi itu sendiru justru memberikan ruang untuk manusia agar bisa mengidentifikasi dan memahami dunia yang tadinya hanya dipahami lewat dikotomi barat dan timur. Konsep itu tidak hanya membantu kita untuk menempatkan diri dengan lebih baik, tetapi juga untuk menemukan berbagai keunikan dalam diri kita (antar manusia) yang tidak bisa disamakan dengan orang lain (self-othering others atau membedakan diri dengan yang lain). Dengan demikian, konsep ini (globalisasi) secara tidak langsung telah memengaruhi cara kita memahami dan menuliskan sejarah, menetapkan batas-batas geografis, membingkai budaya, serta membentuk persepsi individual maupun kesadaran kolektif kita.
Salah satu contoh perspektif yang terbentuk adalah dalam gaya berpakaian misalnya. Ketika kita melihat seseorang berpakaian terbuka, maka kita seringkali menganggapnya berperilaku kebarat-baratan dan melanggar budaya ketimuran yang berlaku di Indonesia. Padahal, persepsi tersebut merupakan hasil dari asumsi kolektif yang telah secara sengaja dibenturkan. Sementara, gaya berpakaian sendiri adalah suatu bentuk ekspresi yang terus berevolusi, yaitu sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pakaian sehari-hari masyarakat Indonesia sebelum bertemu pengaruh asing juga mungkin bisa dibilang lebih terbuka dari pakaian sehari-hari zaman sekarang.
Contoh lainnya adalah penolakan terhadap pengakuan gender di luar perempuan dan laki-laki. Penolakan itu terjadi karena banyak orang menganggap bahwa gagasan tersebut sebagai sesuatu yang dipopulerkan oleh dunia barat. Padahal, masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal konsep yang sama dari dahulu kala.
Masyarakat Bugis misalnya, diketahui mengaku adanya lima gender; orowane (laki-laki), makkunrai (perempuan), calabai (berjenis kelamin laki-laki, berpenampilan perempuan), calalai (berjenis kelamin perempuan, berpenampilan laki-laki), dan bissu (interseksual).
Ketika kita gagal atau menolak untuk memahami kedua konsep itu dengan baik, maka kita bisa terperangkap dalam stereotip yang melekat pada barat dan timur itu sendiri. Konsep barat dan timur secara tidak sadar memang membentuk cara memahami manusia yang dikotomis dan hanya bisa melihat dua konsep yang berseberangan dari narasi yang dibentuk oleh pandangan mayoritas. Meski begitu, pertukaran yang terjadi antara barat dan timur ini masih bisa kita pandang sebagai kesempatan untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan dunia di sekitar kita.
Ketidakpedulian terhadap konsep dan sentimen terbukti dapat memicu terjadinya “cultural appropriation” (apropriasi budaya) atau keacuhan terhadap sejarah, identitas dan nilai-nilai budaya, dan apalagi memahami dan mengapresiasinya.
Contoh lain, ketika ramai-ramai sang artis Agnes Monica terus dikritik karena menata rambutnya dengan model cornrow, atau ketika Nagita Slavina ditunjuk sebagai Duta PON XX Papua dan menggunakan busana adat Papua. Sementara pelekatan simbol kebudayaan tersebut dilandasi oleh kebutuhan yang sifatnya lebih komersial ketimbang dari bentuk penghormatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sentimen terhadap konsep budaya barat dan timur senantiasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahkan, sentimen tersebut secara khusus dibentuk oleh persepsi seseorang mengenai kelompok tertentu, yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang melekat dan menjadi bagian diri mereka.
V. Pandangan Sejarawan Tentang Dikotomi Dunia Timur Dan Barat
Dalam konsepnya, bahwa keberadaan dunia timur dan barat bukan melulu batas geografi melainkan lebih pada kesamaan budaya. Bahkan sejak dulu, kita tidak asing lagi dengan sebutan bahwa dunia timur adalah ramah, sopan dan tradisional sedangkan dunia Barat dikenal lebih intelektual, terbuka dan modern. Persepsi itu diperkuat oleh akibat doktrinisasi pembelajaran di sekolah-sekolah. Memang tidak ada salahnya menciptakan persepsi seperti itu karena memang faktanya demikian, meskipun tidak serta merta 100% sesui. Bahkan, dikotomi timur-barat dalam pemberitaan di media-media global seringkali digunakan dengan istilah negara Barat dan negara Timur. Contohnya, dalam perang Ukraina dan Perang Gaza yang belakangat terus berkecamuk itu, bahwa dikotomi Timur-Barat mencuat kembali dimana pihak yang mendukung Ukraina dan Israel disebut Negara Barat dan sebaliknya yang mendukung Rusia dan Palestina diibaratkan sebagai Negara Timur.
Dari hal tersebut, seakan-akan dunia ini hanya terpolarisasi menjadi dua kubu saja yaitu Timur-Barat. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan dikotomi Barat dan Timur itu? Apakah dikotomi itu menyangkut soal geografis atau ada faktor lain yang melatar belakangi istilah tersebut muncul? Beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa istilah Timur-Barat itu muncul akibat persepsi perbedaan antara kebudayaan timur dan barat. Selain itu modernisasi juga berperan penting dalam memunculkan dikotomi itu, meskipun masih banyak dipertentangkan oleh para sejarawan lain yang memiliki kriteria yang berbeda-beda.
Kemudian negara yang terletak di Asia dan Timur Tengah misalnya, yakni dengan corak keagamaan yang kental seperti Islam, hal itu dikelompokkan sebagai Dunia Timur. Sedangkan Australia, Kanada, Eropa, Selandai Baru dan Amerika serikat dikelompokkan sebagai Negara Barat. Hal itu lebih kepada kesamaan kebudayaan dan sejarahnya, sehingga dalam hal ini letak kawasan (geografis) sudah tidak lagi relevan. Sebut saja negara Rusia yang letak geografisnya berada di wilayah Eropa dan Asia namun dalam perspektif geopolitik disebut sebagai dunia timur setara dengan Cina.
Sementara negara yang letaknya nun jauh dari akar budaya barat seperti Australia dan Selandia Baru yang nota bene secsra geografis lebih dekat ke timur, tapi karena di bidang politik kenegaraannya dikuasai oleh penduduk keturunan Eropa, malah dinamakanlah atau digolongkan sebagai negara Barat. Dari hal-hal seperti itu dapat disimpulkan bahwa batasan dunia Timur dan Barat lebih bersifat kultural dan bersifat hegemoni politik dibandingkan geografis. Sehingga telah menjadi konsensus umum bahwa negara yang corak budayanya mirip dengan budaya Islam dimana pun letaknya masuk kelompok timur, sementara Australia dan Selandia Baru yang masuk dunia barat karena budayanya memang hasil impor bangsa-bagsa Eropa. Bahkan, batasan dikotomi itu menjadi semakin bias ketika daerah dengan kebudayaan beragam seperti yang terjadi di daerah Balkan dan rumpun kaukasus (perbatasan Asia dan Eropa). Di wilayah itu malah warganya dapat menyatakan dirinya bagian dari timur atau barat sesuai etnis dan agama yang dianut.
Bahkan, jika melihat karateristik fisik, manusianya lebih condong ke Eropa yang menjadi akar negara Barat. Sebaliknya, dalam kehidupannya sangat kental dengan budaya ketimuran. Di daerah Balkan dan rumpun kaukasus itu, dalam suatu negara terdapat kental budaya Islam dan Kristen. Sementara bagian wilayah berpenduduk Islam menganggap bagian dari timur sedangkan wilayah yang mayoritas Kristen mendeklarasikan sebagai diri bagian barat. Dikotomi Timur-Barat sepertinya tidak jauh berbeda dengan istilah negara maju dan negara berkembang yang umumnya terletak di bagian bumi utara dan selatan. Namun lambat laun beberapa negara di selatan bumi mulai menjadi setara dengan negara maju sehingga istilah tersebut saat ini tidak relevan lagi.
Nah, kondisi dunia yang dinamis dan multipolar seperti saat ini, dikotomi Timur-Barat juga tidak menutup-kemungkinan suatu saat akan mencair sendiri dan tidak dibutuhkan lagi karena sesuai perkembangan zaman dan budaya itu sendiri sifatnya dinamis.
VI. Mitos Dikotomi Budaya Timur Dan Barat
Sudah menjadi rahasia umum kalau banyak masyarakat kita hingga saat ini, baik kalangan akademik maupun non-akademik, baik elit maupun non-elit, yang masih tetap memberi dikotomi antara budaya Barat dan budaya Timur. Sementars kata “Barat” itu sendiri mengacu pada negara-negara di Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Eropa Barat, atau Australia dan Salandia Baru. Singkatnya, budaya Barat mengacu pada “budaya bule”. Sementara kata “Timur” itu sendiri merujuk pada kawasan Asia, termasuk Asia Timur dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia). Budaya Barat, oleh masyarakat kita biasanya dicirikan berwatak intelektualis, individualis, selfish, kapitalis, liberalis, sekularis, ateis, berorientasi profit dan lain sebagainya. Sementara budaya Timur digambarkan berwatak nyaris berlawanan dengan budaya Barat, yakni spiritualis, teis, agamais, kolektivis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, budaya Barat kerapkali diberi label atau stigmatisasi negatif. Misalnya, tidak mengenal sopan-santun, biadab, gemar berperang dan melakukan tindakan kekerasan (seperti zaman kolonial), perilaku seks bebas (“kumpul kebo”), minim solidaritas sosial, tak peduli tradisi lokal dan lain sebagainya. Sedangkan budaya Timur seringkali dilabeli dengan hal-hal yang bersifat positif seperti ramah, sopan santun, penuh perdamaian, tidak suka kekerasan, gemar menolong sesama, peduli tradisi lokal, dan lain sebagainya.
A. Dikotomi Hanya Mitos Belaka
Pada praktiknya, dikotomi itu hanyalah mitos belaka. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teman penulis (beberapa mahasiswa dan sekaligus menjadi sarjana) yang nota bene mereka pernah lama tinggal di Barat. Mereka menilai, bahwa segregasi hitam putih budaya Timur-Barat itu hanya ada di alam imajinasi saja katanya. Tidak ada di dunia nyata atau hanya ada yang benar sebagian. Sementara narasi tentang budaya Barat yang serba buruk dan negatif atau budaya Timur yang serba baik dan positif itu sama sekali tidak valid. Faktanya, baik-buruk atau positif-negatif ada di dunia Barat maupun Timur. Sejumlah karakteristik dan stigmatisasi yang selama ini dialamatkan ke budaya Barat juga ada di budaya Timur. Begitu pula sebaliknya. Sejumlah labelitas dan karakteristik yang selama ini disematkan ke budaya Timur juga ada di budaya Barat. Misalnya, Barat bukan hanya rumah bagi kaum intelektualis tetapi juga kelompok spiritualis. Ada banyak individu dan kelompok spiritual di negara-negara Barat, termasuk ordo-ordo Sufi, komunitas yogi, kaum spiritualis Budhis, pengikut gerakan New Age, masyarakat teosofi, dan lain sebsgainya. Sebaliknya, Timur juga bukan hanya rumah bagi kelompok spiritualis dan mistikus tetapi juga ada aneka ragam kelompok intelektual para ilmuwan. Jadi, dikotomi “intelektualitas Barat” versus “spiritualitas Timur”, saat ini nampaknya sudah tidak lagi relevan. Bahkan kini negara-negara seperti China, Taiwan, Jepang, dan Korsel sedang gencar membangun berbagai pusat pendidikan, teknologi, dan universitas kelas dunia yang akan menjadi kiblat peradaban intelektual dan teknologi di masa depan.
Hasilnya kini banyak Universitas di Asia yang masuk jajaran kampus top dunia dan berpotensi untuk menggeser dominasi Barat di masa mendatang. Bahkan saat ini, sejumlah negara di Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk Arab seperti UEA, Qatar, dan Arab Saudi juga sedang berlomba-lomba untuk membangun Universitas berkelas dunia, yaitu yang bertumpu pada kemajuan teknologi canggih (seperti Artificial Intelligence), riset ilmiah, dan spirit intelektualisme. Negara Arab Saudi misalnya, saat ini sudah membangun sebuah kampus prestisius berkelas Internasional seperti “King Abdullah University of Science and Technology”. Oleh karena itu, asumsi bahwa Barat yang diidentikkan dengan sekularisme, liberalisme, atau ateisme dan agnotisisme juga tidak selamanya akurat karena banyak kelompok militan-konservatif berbasis agama di Barat yang sangat anti terhadap doktrin-doktrin sekularisme dan liberalisme serta mengecam berbagai praktik sosial yang mereka anggap tidak religius.
Bahkan, sejak beberapa dekade silam, tentang fenomena “public religion”, sebuah proses deprivatisasi agama dimana agama memainkan peranan sentral di ranah publik, tengah menjangkiti sebagian negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Fenomena itu mendorong (alm) Prof. Dr. Peter L. Berger, yakni seorang sosiolog ternama yang juga salah seorang mantan Guru Besar di Universitas Boston (AS), untuk merevisi tesis klasiknya tentang sekularisasi agama dalam bukunya yang berjudul “The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics”. Meskipun dunia Timur (khususnya Timur Tengah, India, dan China) memang tempat lahirnya berbagai agama dunia, namun saat ini nampaknya bibit-bibit sekularisme dan liberalisme juga hadir di kawasan tersebut, yang diperkenalkan oleh berbagai kelompok seperti akademisi, ilmuwan, teknokrat, politisi, pemerintah, pebisnis, dan lain sebagainya, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II.
B. Budaya Individualis Versus Budaya Kolektivis
Kemudian karakteristik Barat sebagai “masyarakat individualis” (individualist society) yang diasumsikan secara keliru oleh sebagai masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan tidak mempunyai kepekaan, kepedulian, dan solidaritas sosial juga tidak sepenuhnya besar. Faktanya, saat ini banyak kelompok filantrofi dan lembaga karitas untuk misi kemanusiaan global menjamur di Barat. Masyarakat Barat juga sudah terbiasa menggalang dana (fundraising) dengan berbagai cara untuk berbagai program kemanusiaan, pendidikan, beasiswa, dll, baik untuk masyarakat yang tinggal di negara-negara Barat maupun di berbagai negara di dunia ini. Misalnya, Mennonite Central Committee yang mempunyai program kemanusiaan global di hampir semua negara di jagat ini. Sementara itu, Timur yang selama ini dilabeli “masyarakat kolektivis” (collectivist sosiety) yang diandaikan gemar menolong sesama, saling membantu serta meminimalisir watak dan perilaku egoistik dan individualistik, dalam praktiknya tidak selamanya terjadi. Lihat saja misalnya budaya gotong royong atau kerja bakti yang dulu menjadi karakter masyarakat kini sudah luntur. Demikian pula, banyak orang tidak memperdulikan yang lain saat mengantri bantuan, pembagian sembako, atau pada waktu ada acara ngantri di sarana publik (di Bank). Dari pengamatan sederhana itu kita bisa tahu karakter budaya kolektivis masyarakat Timur tidak selamanya akurat. Solidaritas sosial, kalaupun terjadi, biasanya hanya pada kelompok kecilnya saja tidak melintas batas agama, etnis, dan kemanusiaan.
C. Kebiadaban Versus Keberadaban
Karakteristik lain yang tidak akurat adalah memberi stigma Barat sebagai masyarakat yang penuh kekerasan (seperti zaman kolonial) dan Timur sebagai masyarakat yang penuh perdamaian atau Barat diidentikkan dengan kebiadaban dan Timur dengan keberadaban. Barat memang memiliki sejarah kelam yang penuh kekerasan seperti ketika zaman kolonialisme, imperialisme, perang, ethnic cleansing, rasisme, “barbarianisme”, dan lain sebagainya, baik terhadap penduduk lokal maupun asing. Tetapi Timur juga tidak luput dari kekerasan.
Dengan kata lain, substansi kolonialisme, imperialisme, perang, ethnic cleansing, rasisme, “barbarianisme”, dan lain sebagsinya, bukan hanya monopoli dunia Barat. Jika Barat pernah memiliki Hitler atau Mussolini, Timur pernah mempunyai Pol Pot atau Amangkurat I yang sangat bengis. Kini, masyarakat Timur yang dicitrakan penuh cinta, kasih sayang, perdamaian, kerahamahan, dan toleransi itu seolah-olah sirna dari bumi Pertiwi karena berbagai kejadian dan aksi kekerasan yang tak luput juga silih berganti seolah tak ada henti seperti kasus-kasus persekusi, pengeroyokan, pemukulan dan lain sebagainya.
D. Kesimpulan
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengambil hal-hal bersih, baik, dan positif darimanapun datangnya (Barat-Timur, Utara-Selatan) serta menyingkirkan hal-hal kotor, buruk, dan negatif darimana-pun berasal, baik dari negeri sendiri maupun mancanegara. Indonesia akan menjadi bangsa besar jika mampu melakukan hal itu. Sebaliknya, Indonesia akan tersungkur menjadi bangsa kerdil jika terus-menerus hidup dalam budaya hipokrisi, memupuk dikotomi Timur-Barat yang sebetulnya hanya ada di alam imajiner belaka.