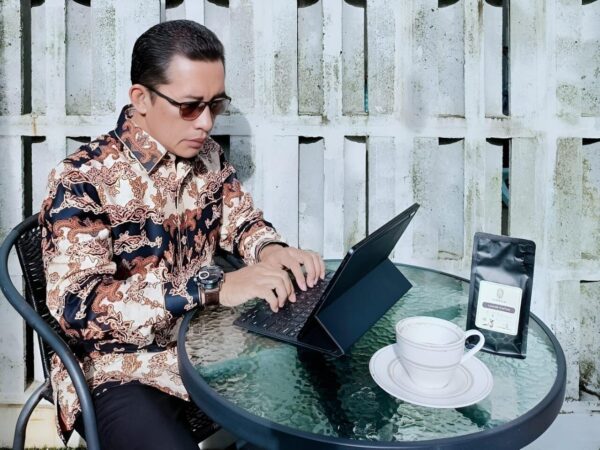Oleh : Dede Sudiarto, S.Pd.,M.M ( Bid.Pend.ICMI BANTEN )
Di atas kertas, Indonesia tampak makin serius menata pendidikan. APBN 2025 kembali memenuhi amanat 20% fungsi pendidikan dengan pagu sekitar Rp724,3 triliun, tertinggi sepanjang sejarah dan per akhir Februari 2025 realisasinya sudah Rp76,4 triliun (10,6%). Pemerintah juga menegaskan belanja pendidikan akan tetap dijaga di kisaran 20% pada tahun-tahun berikutnya. Namun, besarnya alokasi fiskal itu belum otomatis menutup jurang antara retorika “investasi SDM” dan capaian pembelajaran di ruang kelas.
Di sisi akses, capaian Indonesia memang impresif. Partisipasi sekolah (APS) usia wajib belajar dasar nyaris universal: pada 2024, APS nasional usia 7–12 tahun tercatat sekitar 99,19%. Artinya, hampir semua anak usia SD masuk sekolah. Tetapi gambaran berubah ketika usia semakin tinggi: berbagai rilis BPS menunjukkan penurunan signifikan di kelompok 16–18 tahun dan lebih tajam lagi di 19–23 tahun. Retorika pemerataan akses karenanya harus diimbangi strategi menahan “kebocoran” partisipasi saat transisi SMP–SMA dan SMA–PT.
Masalah pokok ada pada mutu belajar. Hasil PISA 2022 (dirilis 5 Desember 2023) menempatkan Indonesia jauh di bawah rata-rata OECD pada matematika, membaca, dan sains. Yang lebih mengkhawatirkan, hanya 18% siswa Indonesia mencapai level kecakapan minimum (Level ≥2) di matematika; 25% di membaca; dan 34% di sains. Dengan kata lain, mayoritas siswa 15 tahun kita belum menembus ambang literasi dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan belajar.
Namun, paradoks lain muncul: di ruang kelas, nilai rapor dan hasil ujian sekolah sering kali tampak cukup baik, bahkan cenderung tinggi. Fenomena ini memunculkan praktik “hipokritisasi capaian”: prestasi akademik secara angka seolah menunjukkan keberhasilan, padahal jika diuji melalui asesmen internasional, kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir kritis masih rendah. Inflasi nilai (grade inflation) dan kultur “menyembunyikan kegagalan” membuat publik terlena pada simbol capaian, sementara kemampuan realistis siswa seperti problem solving, kolaborasi, atau kreativitas, tidak berkembang optimal.
Indikator global “learning poverty” proporsi anak yang tidak mampu membaca pemahaman pada usia 10 tahun mencerminkan hal serupa. Brief Bank Dunia menunjukkan sekitar 53% anak Indonesia pada akhir pendidikan dasar belum mahir membaca (disesuaikan dengan anak di luar sekolah). Ketika nilai sekolah tidak merepresentasikan realita kompetensi, maka capaian pendidikan hanya berhenti sebagai narasi administratif, bukan refleksi kualitas belajar sesungguhnya.
Di tingkat input, Indonesia tidak kekurangan guru jika dilihat dari rasio murid–guru. Pada tahun ajaran 2023/2024, rasio rata-rata berada di kisaran 13–15 siswa per guru di SMP–SMA/SMK, bahkan lebih rendah dari standar ideal PP 74/2008 (±20:1 untuk SD–SMA; 15:1 untuk SMK). Artinya, tantangan bukan semata kuantitas guru, melainkan distribusi, kompetensi pedagogik, dukungan pengembangan profesional, dan kultur pembelajaran di kelas.
Data PISA juga menyorot ekosistem belajar: hanya 25% siswa melaporkan didukung kelas virtual harian saat penutupan sekolah, dan seperempat hingga sepertiga siswa mudah terdistraksi perangkat digital di pelajaran matematika. Meski sense of belonging siswa Indonesia relatif tinggi, disiplin kelas dan dukungan instruksional masih inkonsisten. Di sinilah semakin tampak “hipokrisi kebijakan”: retorika transformasi digital dan penguatan karakter belum sepenuhnya berwujud praktik mengajar yang berfokus pada pemahaman mendalam.
Pada ranah tata kelola, mandat 20% kerap dipakai sebagai simbol komitmen. Tetapi komposisi belanja antara pusat, transfer ke daerah, hingga pembiayaan, menentukan kualitas output. Beberapa tahun terakhir, porsi besar mengalir melalui Transfer ke Daerah untuk BOS/BOP dan tunjangan guru. Itu penting, namun efeknya pada hasil belajar bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas pendampingan sekolah, dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan. Diskursus publik tentang apakah sebagian program non-instruksional dihitung sebagai “pendidikan” juga mengemuka, menuntut transparansi agar setiap rupiah benar-benar berdampak ke kelas.
Akhirnya, “hipokrit pendidikan” bukan tudingan personal, melainkan cermin struktural: kita relatif berhasil menghadirkan sekolahnya, tetapi belum konsisten menghadirkan belajarnya. Lebih jauh, kita juga cenderung mengemas capaian dalam bentuk angka-angka cantik, padahal kemampuan riil siswa masih rapuh. Jalan keluarnya bukan menambah slogan, melainkan mengunci setiap kebijakan pada indikator hasil belajar nyata, literasi, numerasi, berpikir kritis, dan keterampilan hidup. hingga jurang antara retorika dan kenyataan benar-benar menyempit.