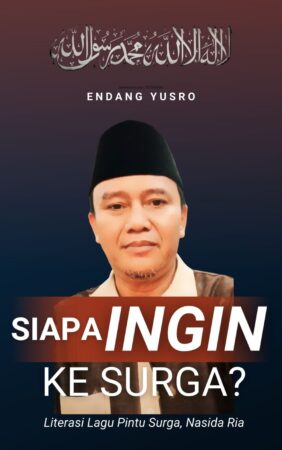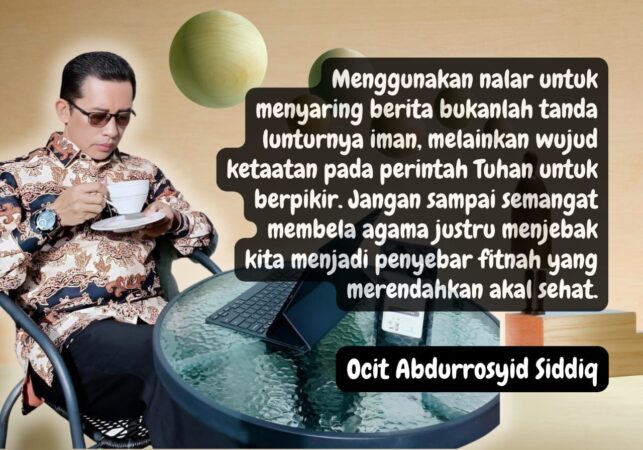Oleh : Adung Abdul Haris
I. Prolog
Cak Nur (Nurcholis Majid) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus-Dur) dianggap pemikiran mereka sangat esentrik dan menggelitik, karena pemikiran kedua tokoh intelektual Islam Indonesia itu sangat modern, pluralis, dan inklusif dalam konteks Islam di Indonesia. Lebih dari itu, Cak-Nur dan Gus-Dur juga menggabungkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Mereka mendorong demokrasi dan kebebasan berpikir, menolak teokrasi dan politik berbasis agama yang eksklusif, serta memperjuangkan hak perempuan dan non-Muslim, meski konsep-konsepnya seringkali memicu kontroversi dan perdebatan khususnya di internal umat Islam Indonesia itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa aspek yang esentrik dan menggelitik dari pemikiran Cak-Nur dan Gus-Dur :
- Pluralisme Dan Inklusivisme Agama.
Mereka mendukung konsep pluralisme yang mengakui keberagaman keyakinan, dan bahkan menganut paham inklusivisme yang berarti “seluruh kebenaran ajaran agama lain ada juga dalam agama kita”. - Penolakan Teokrasi.
Cak Nur dan Gus-Dur menentang gagasan negara Islam atau negara teokrasi, serta mendorong pembangunan Indonesia sebagai negara republik yang menerima demokrasi. - Fokus Pada Keindonesiaan.
Pemikiran mereka mengintegrasikan Islam dengan konteks kebangsaan Indonesia yang pluralistik, bukan sekadar mengikuti nilai-nilai Islam global atau lokal secara dogmatis. - Konsep Modernitas.
Mereka mengartikan modernisasi bukan sebagai westernisasi (peniruan budaya Barat), melainkan sebagai proses rasionalisasi, yaitu perombakan pola pikir dan tata kerja yang irasional menjadi rasional, sejalan dengan hukum alam (sunnatullah). - Peran Gender.
Pemikirannya mereka juga mengembangkan hak-hak perempuan dalam Islam dan isu-isu gender lainnya, menandakan keterbukaan terhadap kemajuan sosial di tengah ajaran agama. Islam Yes, - Islam Yes…Partai Islam No.
Khusus untuk Cak-Nur, ia sempat menggegerkan seantero negeri ini, karena ia sempat mengeluarkan slogan (Islam yes, Partai Islam no), hal itu menunjukkan pandangannya bahwa umat Islam seharusnya fokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik dan sosial, bukan terlibat dalam politik identitas berbasis agama yang ia anggap eksklusif dan memecah belah.
Pemikiran kedua toloh intelektual Muslim diatas, memang dianggap sangat esentrik dan sekaligus menggelitik, karena berada di luar arus utama dan seringkali kontroversial di masanya, akhirnya terus mendorong diskusi tentang Islam yang lebih terbuka dan relevan dengan perkembangan zaman.
II. Refleksi Tentang Gus-Dur Dan Cak-Nur (Sebuah Titik Temu)
“Kita boleh curiga kepada kimia tanah dan sumur udara di Jombang Selatan yang dulu membesarkan Nurcholis Madjid (Cak-Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus-Dur). Pasti terdapat kandungan zat tertentu yang aneh di sana yang mendorong kedua tokoh gila itu, memang rajin menyodorkan hil-hil yang mustahal,” tulis budayawan Emha Ainun Najib atau yang lebih akrab disapa Cak-Nun. Bahkan, di sekitar era tahun 80-an, tulisan Cak Nun diatas, telah tayang di Tempo dengan judul “Tharikat Nurcholishy”. Oleh karena itu, agaknya kita tidak terlampau berlebihan, namun, tentunya kita kita harus sadar bahwa kedua tokoh itu sempat mengharukan biru di Indonesia, khususnya pada tataran alam pemikiran Islam. Bahkan, hingga saat ini kedua tokoh itu, sekalipun keduanya sudah almarhum, namun saat ini masih ramai dibicarakan di banyak tempat, entah itu gagasan mereka, tindakan mereka, atau teladan mereka. Menarik kiranya jika kita terus menelusuri mengapa Gus Dur dan Cak Nur hingga detik ini masih ramai dibicarakan seolah-olah keduanya berada di tengah kita, masih begitu segar terasa. Sementara tulisan pendek Cak-Nun (MH. Ainun Najib) diatas, kiranya akan sedikit menyinggung pertemuan dua tokoh tersebut sekaligus menjawab mengapa Gus Dur dan Cak Nur hingga saat ini masih bisa merasakan kehadirannya.
Islam sebagai agama yang turun ribuan tahun lalu hingga kini telah melewati lintasan sejarah yang panjang dan telah bersentuhan dengan berbagai peradaban. Sebagai penunjuk jalan kehidupan umat manusia, ajaran agama Islam senantiasa dituntut untuk merelevansikan ajarannya dengan zaman, sehingga Islam yang turun ribuan tahun lalu bisa menyesuaikan dengan konteks zamannya. Tidak terkesan tertinggal, apalagi terus kaku dan baku. Dalam hal inilah istilah pembaruan Islam muncul. Pembaruan Islam bukanlah semata-mata untuk mengubah ajaran Islam yang telah mapan, melainkan sebuah upaya untuk menampilkan ajaran agama Islam agar lebih men-zaman dan kontekstual. Pembaruan Islam merupakan respons terhadap realitas dan tuntutan aktual tertentu, baik yang mencakup doktrin keagamaan maupun realitas sosial, seperti ekonomi, politik, dan adat.
Di sini Gus Dur dan Cak Nur hadir, kedua tokoh itu hadir menjawab kebutuhan zaman, dimana Islam tengah dikepung oleh modernitas, globalisasi, dan seolah-olah belum siap menyesuaikan diri dengan zamannya. Gus Dur dan Cak Nur dengan kedalaman dan keluwesan ilmunya, mereka menawarkan gagasan segar dan inovatif-terobosannya. Gus Dur memiliki pandangan dasar bahwa Islam harus secara aktif dan substantif menjadi sumber daya dan kemudian dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan modernitas.
Pemmahaman ajaran Islam akan terus-menerus mengalami pembaruan sesuai dengan aspirasi yang terus berkembang di kalangan masyarakat yang memeluknya. Antara lain bentuk gagasan yang ditawarkan Gus Dur adalah tentang demokrasi. Bagi Gus Dur, demokrasi adalah persamaan hak, menghargai pluralitas, tegaknya supremasi hukum, terciptanya keadilan serta kebebasan menyampaikan aspirasi. “Perjuangan menegakkan demokrasi menjadi inti kehidupan saya” ungkap Gus Dur. Sejalan dengan itu, proses penegakan demokrasi pada persamaan akan menekankan pada nilai egalitarianisme dan pluralisme. Semuanya saling berkelindan. Sementara itu, Cak-Nur tidak kalah tangguhnya, ia juga ikut mendorong transformasi masyarakat Muslim untuk merespons dinamika sosial yang terus berubah. Hal itu terbukti dari berbagai serakan tulisan Cak-Nur yang demikian progesif untuk menyikapi perubahan zaman. Gagasan sekularisasi misalnya, sekalipun banyak tantangan, tapi ia terus berjalan dan pada akhirnya bisa diterima.
Sedangkan gagasan tentang sekularisasi yang terkandung dalam pemikiran Cak-Nur, yaitu bagaimana umat Islam, agar mampu menduniawikan nilai-nilai yang sudah seharusnya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawikannya. Hematnya, sekularisasi yang ditawarkan oleh Cak-Nur itu, memang bukan dimaksudkan untuk standar sekularisme lalu mengubah umat Islam menjadi sekuler.
Nampaknya, diantara titik temu antara Gus Dur dan Cak Nur, memang keduanya tampil sebagai seorang tokoh yang selalu berusaha menyesuaikan ajaran Islam, menampilkan wajah baru Islam yang lebih progesif dan inklusif. Keduanya tampak tengah berusaha melakukan proyek-proyek tentang pemahaman perlunya pemahaman Islam kembali agar ia (Islam) tangguh dalam merespons perubahan-perubahan sosial-budaya yang begitu cepat terjadi.
Selain apa yang disebut diatas, baik Gus-Dur dan Cak-Nur keduanya adalah santri tulen asal Jombang dan memiliki rantai keilmuan yang sama, yakni kepada KH Hasyim Asy’ari. Sama-sama belajar kitab kuning dan sama-sama belajar kitab-kitab putih. Gus Dur Jombang-Kairo sementara Cak Nur Jombang-Chicago. Lalu mengapa hingga kini kedua tokoh itu masih terasa begitu segar di ingatan kuta? Oleh karena itu, kiranya perlu kembali kita renungkan sebuah ungkapan yang berbunyi : “Ketika sesosok manusia dipuji sekaligus dibenci, ketahuilah dia adalah seorang tokoh besar, orang yang hebat.” Baik Gus-Dur dan Cak-Nur keduanya adalah tokoh yang satu kali banyak dipuja-puji, namun di lain waktu tidak sedikit juga terang-terangan ia dicaci-maki habis-habisan. Memang begitulah alamiahnya sesosok tokoh besar, ia mendapat pujian sekaligus juga menerima cacian. Bahkan, ada sebuah syair yang berbunyi
أَخُو الْعِلْمِ حَيُّ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَوْصَــــالُهُ تَحْتَ التُّرَابِ رَمِيْـــــمُ
“Seorang intelektual ia akan lestari hidup setelah wafatnya, meskipun tulang belulangnya telah hancur digilas bumi.”
III. Nurcholish Madjid (Cak-Nur) Dan Ide Pembaharuan Islam
Prof. Dr. Nurcholish Madjid (1939-2005), yang akrab dengan panggilan Cak-Nur, merupakan tokoh intelektual Islam di Indonesia yang mengusung ide-ide pembaharuan Islam. Ia berasal dari latar belakang keluarga Kiyai tradisional di Jombang, Cak-Nur mendapatkan pendidikan dasar-dasar keislaman sejak dini di sekolah Madrasah al-Wathaniyah di Mojoanyar yang didirikan ayahya, KH Abdul Madjid. Kemudian, Cak-Nur nyantri di pesantren Darul Ulum Rejoso (1955). Sejak belia, Cak Nur sudah akrab dengan dunia “kitab kuning” atau literatur keislaman tradisional. Dari ayahnya pula, yang merupakan tokoh politik Masyumi, ia mewarisi bakat yang kuat tentang aktivisme dan politik Islam. Bahkan, pendidikan keislamannya semakin matang setelah menempuh pendidikan Islam bergaya modern di Pesantren Darussalam Gontor (1960). Di mata pemimpin pesantren Gontor, KH. Imam Zarkasyi, Cak Nur adalah seorang santri yang cerdas, berbakat, kritis, dan memiliki wawasan keislaman yang luas. Oleh karena itu Cak-Nur termasuk menjadi “santri kinasih” (santri menonjol yang special di mata Kyai) Kyai Zarkasyi. Setelah lulus dari Gontor, Cak Nur melanjutkan studi sarjana di bidang sastra Arab di UIN Syarif Hidayatullah (1968).
Cak-Nur mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan doktoral dalam bidang studi Islam (Islamic Studies) di Universitas Chicaco Amerika Serikat (1984), dan menulis disertasi “kritik teologi dan filsafat” berjudul: “Ibn Taimiyya on Kalam and Falsafa”: (A Problem of Reason and Revelation in Islam). Selama belajar di Amerika itulah Cak Nur banyak terinspirasi oleh pemikiran tokoh pembaharu Islam dari Pakistan, Fazlurrahman.
Karir Cak-Nur dalam bidang akademik dimulai dengan pekerjaan sebagai peneliti. Ia mengawali sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS)(1978–1984), hingga menjadi peneliti senior (senior researcher) di bidang agama dan filsafat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (1984–2005). Di mata beberapa pegawai LIPI yang membantu dalam pekerjaannya, Cak-Nur adalah sosok yang hangat, ramah, dermawan, dan seringkali membagikan gajinya untuk pegawai-pegawai yang lebih membutuhkan.
Selain menjadi peneliti dalam bidang penelitian agama dan filsafat, Cak-Nur juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga menjadi Guru Besar di Fakultas Pasca Sarjana (1985–2005). Cak-Nur kemudian mendirikan Universitas Paramadina di bawah Yayasan Wakaf Paramadina, dan memimpin Universitas tersebut dari tahun 1998 hingga meninggal dunia pada tahun 2005.
Sejak menjadi mahasiswa tahun 60-an, selain sebagai “pembaca buku” yang tekun, Cak-Nur mulai bersentuhan dengan pergerakan kemahasiswaan dan aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karier organisasinya melejit sampai menjadi ketua umum PB HMI selama dua periode (1966-1969). Semangat organisasi pergerakan tersebut, boleh jadi merupakan buah pendidikan di Gontor yang memang sangat menekankan pendidikan kedisiplinan organisasi dan keterampilan. Sejak muda, pikiran-pikiran politiknya tentang hubungan Islam dan negara dan tesis-tesisnya tentang sekularisasi menuai kontroversi dan menjadikannya terkenal sebagai “Natsir Muda”. Bagi Cak-Nur, kita perlu membedakan tegas antara Islam sebagai lembaga dan Islam sebagai agama. Baginya, Islam tidak perlu menjadi lembaga yang melegitimasi atau menjadi sumber tata kelola politik negara. Oleh karena itu, slogan Cak-Nur yang terkenal pada masa itu “Islam Yes, Partai Islam No!”. Bahkan, politisasi agama justru akan merugikan agama itu sendiri karena terdesakralisasi menjadi instrumen kepentingan politik. Sedangkan kata sekuler, berarti memisahkan agar tidak menjadikan agama yang sakral ke dalam kepentingan-kepentingan yang bersifat profan yang partikular dan sempit.
Sementara aktivisme dalam gerakan Islam mengantarkannya bertemu dengan banyak tokoh internasional diberbagai negara. Cak-Nur berdialog, bertukar pikiran, dan mengalami perjumpaan intelektual dengan tokoh-tokoh besar di dunia Islam. Bahkan, pemikirannya semakin berpengaruh berkat keberhasilan memimpin HMI dan menjadi “penulis manifesto” Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI (diresmikan dalam kongers ke-10 HMI) yang digunakan sebagai landasan ideologi dan gerakan perjuangan, dan memenuhi kebutuhan gerakan sesuai konteks keummatan-keislaman, kemahasiswaan, dan keindonesiaan.
Lebih dari itu, pemikiran Cak-Nur tercermin dalam karya-karyanya. Sedangkan salah satu upaya Cak-Nur dalam memulai ide pembaharuan Islam, antara lain, dengan menghadirkan karya “Khasanah Intelektual Islam”. Melalui buku tersebut, Cak Nur berhasil menghadirkan pikiran-pikiran besar para intelektual Muslim klasik dan modern paling berpengaruh yang selama ini banyak membentuk peradaban Islam. Lebih dari itu, pikiran dan komentar Cak Nur juga dituangkan dalam pendahuluan buku tersebut, bahwa sejarah perkembangan pemikiran Islam terjadi karena ide-ide progresif dan inovatif dari para intelektual Muslim pada masanya. Umar bin Khatab misalnya, menurut Cak-Nur, adalah prototype seorang pembaharu Islam pada masa klasik, yakni pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Untuk menyebut pembaharu kontemporer, antara lain, Muhammad Abduh. Oleh karena itulah, dalam pandangan Cak-Nur, ide-ide pembaharuan (tajdid) menjadi keniscayaan bagi kemajuan suatu peradaban, termasuk dalam hal ini peradaban Islam yang dicita-citakan.
Selain itu, ide-ide pembaharuan pemikiran Islam Cak-Nur juga tertuang dalam karya-karya yang lain. Sementara karya-karya Cak-Nur yang paling populer antara lain berjudul : “Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia” (1997), “Islam Agama Peradaban”. “Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah” (1995), Islam Agama Kemanusiaan”. “Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia” (1995), “Kaki Langit Peradaban Islam” (1997), “Masyarakat Religius” (1997), “Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan” (1993), “Ibn Taimiyah Tentang Kalam dan Falsafah” (2020), “Perjalanan Religius Umrah dan Haji” (1997), Cita-Cita Politik Islam (1999), “Islam Doktrin dan Peradaban” (2008). Buku yang terakhir ini (kurang lebih 718 halaman). Buku berjudul, “Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Tela’ah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan”. Buku tersebut termasuk karya Cak-Nur paling monumental, karena memuat kumpulan pemikiran Cak-Nur tentang Islam dalam konteks agenda membangun peradaban. Buku tersebut adalah kumpulan makalah-makalah Cak-Nur dalam forum seminar maupun klub kajian agama di Paramadina.
Cak-Nur mengajak kita untuk memikirkan tentang doktrin-doktrin Islam yang menjadi fondasi etis bagi prasyarat suatu peradaban, berangkat dari konsep-konsep etis dalam al-Quran, seperti Islam, iman, ihsan, tauhid, takwa, akhlak, etos kerja, dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran pokok tersebut, akhirnya menjadi corak keberagamaan yang inklusif dan menghormati perbedaan (pluralisme) guna menghadapi sebuah realitas masyarakat yang majemuk. Dalam konteks membangun peradaban itu pula Cak-Nur menekankan pentingnya memahami visi universalisme dan kosmopolitanisme Islam.
Pemikiran Islam Cak-Nur juga tak dapat dilepaskan dari visi mendasarnya tentang al-Quran. Cak-Nur memang manusia unik, karena disamping membawa kontroversi tentang ide-ide pembaharuan pemikiran yang inklusif dan progresif, mengandalkan “nalar burhani” (dalam istilah yang digunakan Abid Aljabiri), tapi ia juga dikenal tak pernah lepas dari mushaf al-Quran ke manapun. Cak-Nur juga pembaca dan pengutip al-Quran yang fasih baik dalam tutur maupun tulisan, mencerminkan sebuah keaktifan “nalar bayani” (masih dalam istilah Abid Aljabiri).
Dengan kata lain, ide-ide pembaharuan Cak-Nur itu merupakan hasil pembacaannya terhadap al-Quran dengan perspektifnya sebagai penafsir modern. Hampir semua ide-ide Cak-Nur merupakan upayanya mendialogkan antara pesan al-Quran dengan kenyataan kemajuan sejarah, ilmu pengetahuan, dan perjuangan cita-cita besar suatu peradaban Islam. Bahkan, spiritualitas atau “nalar irfani” yang dibangun oleh Cak-Nur adalah menuju spiritualitas yang inklusif, yang terbuka dalam memahami perbedaan keimanan dan kemajemukan masyarakat di Indonesia.
Cak-Nur menjelma menjadi salah satu ikon pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Penguasaan literasi keislaman yang mendalam, kemampuan akademik yang mumpuni, keluasan pergaulan intelektual, dan kekuatan aktivismenya, akhirnya membentuk pandangan-pandangan keislamannya yang lebih modern dan pemikiran “Islam substansial” yang berwatak moderat, inklusif, kontekstual, dan selalu berdialog dengan ide-ide modernitas (seperti negara bangsa, demokrasi, kesetaraan, dan humanisme), serta mengedepankan kepentingan kebangsaan atau keindonesiaan. Pemikiran Islam seperti itu yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat berperadaban maju (masyarakat madani).
Sebagai bentuk pengakuan atas pemikiran Cak Nur, beberapa tokoh Muslim dan peneliti dari dalam dan luar negeri mencoba menuliskan dan memberikan komentar terhadap ide-ide pembaharuan Islam Cak Nur, disandingkan dengan dua pemikir sezaman yang memiliki banyak kesamaan dalam ide-ide keislaman progresif, yakni Ahmad Syafii Ma’arif (Buya Syafii) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka mencoba menunjukkan bahwa ide-ide “trio” pemikir Islam Indonesia tersebut sejatinya layak menjadi inspirasi bagi pembangunan dunia Islam yang lain, terutama yang sedang bergelut dengan demokratisasi masyarakat Muslim. Diharapkan, upaya pembacaan ulang terus-menerus semacam itu, tidak hanya menjadi ajang transmisi ide-ide pembaharuan, tetapi juga menjadi media reproduksi dan reaktualisasi gagasan pembaharuan Islam di masa depan.
Akhirnya, para pengikut maupun murid-murid dari Cak-Nur terus mengembangkan gagasan besar pembaharuan Islam Cak-Nur, antara lain, menginisasi Nurcholish Madjid Studies dan Nurcholish Madjid Society (NMSC). Para aktivis NMSC dan beberapa penerus ide-ide pembaharuan Cak-Nur, hingga saat ini berhasil mengkompilasi tulisan-tulisan Cak-Nur di berbagai forum dan media menjadi versi karya lengkap Nurcholish Madjid, sehingga dapat diakses ke publik secara meluas. Sementara sluruh karya tulis dari Cak-Nur, akhirnya dapat dilacak juga secara luas (melalui e-book dll).
A. Cak-Nur : Dari Pemikir Hingga Kandidat Calon Presiden RI
Pemikir, budayawan, cendekiawan, dan masih banyak sederet sebutan yang mengantre di belakang nama Nurcholish Madjid atau biasa disapa Cak Nur. Pemikir hebat ini lahir di Jawa Timur, tepatnya di Jombang, pada17 Maret 1939 silam atau 26 Muharram 1358 Hijriyah. Cak Nur kecil dibesarkan dalam lingkungan politik yang kental dan di sekitar Kiyai terpandang di Mojoanyar, Jawa Timur. Ayahnya, KH Abdul Madjid, dikenal sebagai pemimpin Masyumi. Setelah melewati pendidikan di pesantren Gontor, Ponorogo, serta menempuh studi kesarjanaan di UIN Jakarta (1961-1968), mantan Ketua Umum PB HMI itu menjalani studi doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984). Pemikiran Nurcholish Majid atau Cak-Nur yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta itu, ketika ia melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no” pada tahun 1970-an. Bahkan, pemikiran politik Nurcholish Majid (Cak-Nur) semakin memasuki ranah filsafat setelah ia kuliah di Chicago, Illinois, Amerika Serikat itu. Sedangkan tujuan utama kuliah di Universitas tersebut, yaitu untuk meraih gelar doktor dalam bidang filsafat.
Di era tahun 1970-an, Cak-Nur atau Nurcholish Majid, saat itu terlibat perdebatan segitiga yang begitu seru dengan Amien Rais dan Mohamad Roem. Pemicunya adalah tulisan Amien Rais di majalah Panji Masyarakat (Panjimas), “Tidak Ada Negara Islam”. Cak Nur pun disebut-sebut sebagai tokoh Islam yang berasal dari lingkaran Islam borjuis. Bahkan, gagasan Cak-Nur tentang sekularisasi (menghindarkan umat Islam dari kecenderungan mengukhrawikan persoalan duniawi tanpa kecuali gagasan negara Islam) dan modernisasi (menganjurkan umat berpikir rasional dengan mendukung pembangunan) pernah dinilai sebagai strategi Cak-Nur, untuk mengeles dari rezim (Orde Baru), agar komunitas Islam borjuis tidak terus-menerus larut dalam trauma kepahitan politik, yakni ketika dibubarkannya Masyumi. Ketokohan Cak Nur tetap tak meredup sampai akhir hayatnya. Karena, di tahun 2003, nama Cak-Nur, mulai jadi buah bibir kembali.
Bahkan, pihak media massa saat itu sangat gencar memberitakan bahwa sebelas partai politik akan mangajukan nama Cak-Nur untuk mencalonkan diri sebagai Presiden di pemilihan umum 2004. Ia pun menyatakan bersedia asal beberapa syarat dipenuhi, yaitu antara lain penghormatan supremasi hukum, pembedaan tugas yang jelas antara legislatif dan eksekutif, dan jaminan kebebasan pers. Namun, ada juga yang menyarankan Cak Nur menolak terutama pengajuan dari Partai Golkar. Mereka khawatir arus di Golkar dan partai lain akan menyeret Cak Nur dalam permainan dan cuma menjadi alat politik untuk mengumpulkan suara dalam pemilu 2004. Akhirnya, menjelang konvensi Golkar untuk menentukan calon Presiden, Cak-Nur mundur dari pencalonan. Dia merasa untuk menjadi calon Presiden dari Golkar itu harus memiliki gizi (banyak uang), dan dia tidak memiliki syarat itu. Ini sentilan Cak Nur yang cukup ramai kala itu. Lepas dari pencalonannya sebagai presiden, Cak-Nur sering disebut sebagai intelektual Islam Indonesia yang fasih berbicara tentang Islam di Indonesia. Kalau diajak bicara soal agama dan kebudayaan, ia mampu menjelaskan dengan alur begitu runut, teratur, dan mudah dimengerti.
IV. Gus-Dur Dan Cak-Nur
Ketika saat Gus-Dur wafat, saat itu tiba-tiba mengingatkan kita semua, yaitu akan sosok Cak-Nur. Bahkan, antara Gus-Dur (Abdurrahman Wahid) dan Cak-Nur (Nurcholish Madjid) memang dua sosok santri “par excellent” yang sama-sama dari Jombang (Jawa Timur) yang keduanya sangat besar pengaruhnya dalam dunia pemikiran kaum santri di Indonesia. Karena, keduanya adalah pemikir sekaligus aktivis sosial yang sangat berjasa untuk menarik gerbong dunia pesantren yang semula berada di pinggiran lalu masuk ke gelanggang percaturan intelektual dan politik di Indonesia kontemporer bahkan ke level internasional.
Dua sosok pemikir itu mampu mengintegrasikan pemikiran tradisional dan moderen, lokal dan nasional, dalam semangat dan komitmen Ke-Indonesiaan sehingga semangat islamisme, modernisme dan nasionalisme tidak relevan lagi diperhadapkan. Khususnya bagi dunia pesantren, Gus-Dur dan Cak-Nur, mereka telah mendongkrak sikap percaya diri secara kultural dan intelektual sehingga pesantren yang semula dianggap eksotik, kumuh, terbelakang, lalu berubah menjadi pusat kaderisasi intelektual dan pemikir kebangsaan dengan faham keagamaannya yang moderat dan inklusif. Gus-Dur sendiri keelrapkali bercanda “bahwa Jombang telah melahirkan seorang-orang gila di negeri ini”, yakni ia kerapkali menyebut Cak-Nur, Emha Ainun Najib atau Cak-Nun, dan dirinya sendiri. Mereka adalah sosok-sosok pribadi yang berani berbeda dan siap menerima resiko. Oleh karenanya Gus-Dur, Cak-Nur, dan Cak-Nun akan tercatat dalam sejarah sebagai pejuang demokrasi yang tumbuh dari rahim dunia pesantren.
Cak Nur lahir 17 Maret 1939, meninggal 29 Agustus 2005, sedangkan Gus-Dur lahir 4 Agustus tahun 1940, meninggal 30 Desember tahun 2009. Bagi para pejuang demokrasi dan kemanusiaan, dua sosok intelektual-aktivis itu serasa masih hidup meski keduanya telah lebih dahulu kembali ke rahmatullah, yakni untuk selama-lamanya. Beruntung-lah pikiran-pikiran mereka sebagian sudah terabadikan dalam buku sehingga kita lebih leluasa dan obyektif untuk membaca dan menilainya. Bahkan, ketika Gus-Dur wafat, terutama di hari pemakamannya yang ternyata dibanjiri oleh air mata umat itu, dan bahkan jutaan orang di negeri ini (termasuk yang dirasakan oleh penulis) kerapkali merasa kehilangan dan kerapkali juga bergumam di hati. “Gus Dur memang orang luar biasa…!! Karena, amplitudo getarannya baru terasa penuh pada detik-detik ketika beliau wafatnya”.
Benarlah kata orang bijak, dengan memberi kamu menerima, dengan memaafkan kamu dimaafkan, dengan mati kamu hidup abadi. Tentu tak akan habis-habis orang membicarakan Gus Dur, karena pemikiran dan sepak terjangnya yang multidimensi, kontroversial dan di luar dugaan kebanyakan orang. Dan hingga saat ini, telah banyak buku terbit yang isinya mengulas pemikirannya. Sebagai orang yang pernah mencicipi dunia akademik, tentu penulis akan terus mendorong temen-temen (khususnya para penulis esai dll), untuk meneliti dan mengkajinya kembali secara ilmiah karena begitu banyak tesis atau pemikiran Gus-Dur maupun Cak-Nur, yang sangat relevan untuk membangun wacana keislaman dan keindonesiaan hari ini.
A. Sama-Sama Dari Jombang (Jawa Timur)
Di samping keduanya lahir di kota yang sama, Jombang, Jawa Timur, beberapa pemikiran Cak-Nur (Nurcholish Madjid) dan Gus-Dur (Abdurrahman Wahid) memiliki kesamaan serta pengaruh yang besar bagi perkembangan politik Islam di Indonesia. Secara intelektual, kedua orang itu memiliki akses ke khazanah keislaman klasik sampai yang kontemporer. Salah satu kelebihan mereka dibandingkan dengan ulama Islam pada umumnya ialah kemampuan dalam mengekspresikan pesan Islam dengan meminjam idiom dan aksioma ilmu pengetahuan sosial yang dipelajarinya dari literatur Barat. Cara itu, di satu sisi, menjadikan pemikiran mereka terasa aktual dan relevan dengan persoalan modernitas. Tapi, di sisi lain, realitanya mudah menimbulkan kesalahpahaman bagi umat Islam yang kurang akrab dengan idiom-idiom ilmu pengetahuan sosial. Pendekatan empiris-induktif, yang sering digunakan baik oleh Cak-Nur maupun oleh Gus-Dur, dan juga pendekatan hermeneutik dalam upaya untuk mengungkapkan atau membentangkan dimensi pemikiran mereka.
B. Dialog Muda Membangun Karakter Bangsa
Sekitar tahun 2012, tepatnya pada hari Kami, tanggal 15 Agustus 2012, pihak Abdurrahman Wahid Centre Universitas Indonesia (AWC UI) menggelar acara dialog yang bertemakan, “Dialog Muda Membangun Karakter Bangsa: Refleksi Pemikiran Dan Aksi Abdurrahman Wahid (Gus-Dur), Dan Nurcholis Madjid (Cak-Nur)”. Dialog tersebut berlangsung di Ruang Sinema, Perpustakaan UI, Kamis (09/08/2012). Diskusi tersebut dimoderatori oleh Dr. Mahmoud Syaltout, hadir juga Dr. Yudi Latif (Pendiri Nurcholis Madjid Society), Dr. Ahmad Najib Burhani (Pemuda Muhammadiyah, Anggota Maarif Institute), Romo Dr. Benny Susetyo (Sahabat Gus Dur, Cak Nur), serta Ahmad Suaedy, M.Hum. (Komunitas BNU dan AWC UI) sebagai pemateri.
Romo Benny memaparkan, Gus Dur melihat agama tidak hanya sebagai teks yang kaku. “Agama selama ini hanya dilihat sebagai suatu yang kering sehingga memberatkan, bukan malah membebaskan. Gus Dur melihat, agama harus diaktualisasikan ke dalam konteks sehingga tidak kaku dan kita mendapat kebebasan dari perasaan damai yang dicapai,” tutur Romo Benny. Jika Gus Dur menitikberatkan kontekstualisasi, Kang Moeslim berfokus pada kebermanfaatan Islam bagi masyarakat. “Menurut Kang Moeslim, jangan sampai agama hanya dijadikan identitas, tetapi juga lebih mengena di hati masyarakat,” ujar Dr. Ahmad Najib. Sementara menurut Dr. Yudi Latif menjelaskan, pemikiran Cak Noer berkisar pada integrasi Islam dengan budaya ke-Indonesiaan. “Selama ini, Islam dapat berkembang dan diterima dengan baik di Indonesia karena adanya integrasi dengan budaya setempat,” tutur Dr. Yudi Latif (Unversutas Indonesia, 15 Agustus 2012/https; humas.ui.id).
C. Pemikiran Gus-Dur Dan Cak-Nur Tentang Konsep Humanisme Islam
Bahkan, hingga saat ini, sudah ada juga berbagai pihak yang telah melakukan proses penelitian, yakni untuk mencari hubungan antara humanisme Islam yang digagas oleh Gus Dur dan Cak Nur. Sedangkan humanisme adalah suatu ajaran atau pemahaman tentang kemanusiaan. Sementara bentuk humanisme Gus-Dur lebih mengacu pada prinsip kemanusiaan. Sedangkan pada prinsip teologis Cak-Nur, ia lebih mengutamakan prinsip Ketuhanan (keimanan) dalam humanismenya. Sementara tujuan penelitian yang dilakukan baik oleh kalangan individu maupun kelompok peneliti, yaitu guna mengetahui dimensi pemikiran humanisme Gus-Dur dan Cak-Nur terutama tentang konsep humanisme. Sementara untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Gus-Dur dan Cak-Nur, terutama tentang konsep humanisme mereka, pada umumnya para peneli menggunakan penelitian kepustakaan (studi kepustakaan) dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Sedangkan kesimpulan hasil dari sang para penelitian diantaranya :
Pertama, konsep humanisme Gus-Dur merupakan prinsip kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam dan berakhir pada tujuan menciptakan masyarakat yang adil. Kedua, konsep pemikiran humanisme Cak-Nur merupakan prinsip kemanusiaan yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup ini berasal dari dan menuju Tuhan, dan lebih mengutamakan prinsip Ketuhanan. Ketiga, persamaan pemikiran Gus-Dur dan Cak-Nur adalah manusia harus diwujudkan secara adil tanpa membedakan dari segi apapun, yakni mempunyai harkat dan martabat yang sama sedangkan perbedaan dari adanya pemikiran humanisme Gus-Dur dan Cak-Nur adalah ditinjau dari sudut pandang terwujudnya humanisme dalam Islam, prinsip kebebasan dan pengaruh pemikiran.