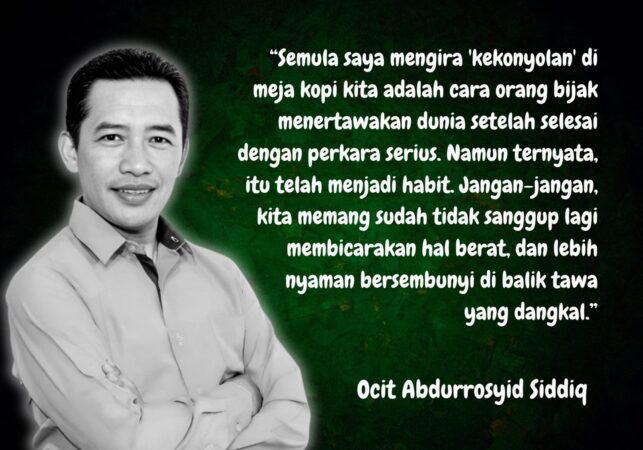Ocit Abdurrosyid Siddiq
Desember 1990, udara kota Malang terasa lebih dingin dari biasanya, namun di sebuah aula universitas, suhu politik justru sedang mendidih. Di sanalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) lahir, disambut dengan gegap gempita, tangis haru, dan takbir yang menggema. Bagi sebagian besar kelas menengah Muslim Indonesia, momen itu adalah sebuah “fajar kemenangan”.
Setelah puluhan tahun dipinggirkan oleh rezim Orde Baru sebagai kelompok yang dicurigai (ekstrim kanan), akhirnya umat Islam—atau setidaknya representasi elitnya—diperbolehkan duduk di meja makan kekuasaan. BJ Habibie, sang jenius teknologi kesayangan Soeharto, menjadi ikon baru: simbol persandingkan harmonis antara “Iptek dan Imtaq”.
Namun, ratusan kilometer dari hingar-bingar Malang, di sebuah rumah sederhana di Ciganjur, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) duduk dengan wajah masygul. Ia menolak bergabung. Bukan karena ia anti-intelektual, melainkan karena matanya yang tajam menembus lapisan kulit peristiwa.
Gus Dur melihat apa yang tidak dilihat orang lain: bahwa “pesta” di Malang itu bukanlah kemenangan umat, melainkan kooptasi negara. Ia cemas, Islam yang agung sedang direduksi menjadi alat stempel kekuasaan.
Di sinilah bermula sebuah benturan peradaban kecil dalam tubuh umat Islam Indonesia. Sebuah dialektika yang melibatkan sahabat karib Gus Dur sendiri, Nurcholish Madjid (Cak Nur). Cak Nur, dengan optimisme seorang “Guru Bangsa”, memilih jalan infiltrasi. Ia percaya bahwa sistem yang korup bisa “diwarnai” dari dalam jika orang-orang baik mau masuk ke dalamnya. Baginya, ICMI adalah peluang sosiologis untuk melakukan mobilitas vertikal umat.
Sedangkan Gus Dur, dengan skeptisisme seorang penjaga gawang demokrasi, memilih jalan oposisi. Ia mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) sebagai antitesis, meyakini bahwa birokrasi otoriter tidak akan pernah bisa diwarnai; ia hanya akan menelanmu bulat-bulat.
Namun, di luar pertarungan strategi politik tingkat tinggi itu, ada fenomena kultural yang jauh lebih menggelitik—dan di satu sisi, memprihatinkan.
Perbedaan mendasar antara gerbong Gus Dur (NU) dan gerbong ICMI saat itu bukan hanya soal politik, tapi soal “rasa” beragama. Warga NU, seperti kita yang lahir dari rahim pesantren kobong di Binuangeun atau pelosok Banten lainnya, berislam selayaknya bernafas. Kita tidak perlu berteriak bahwa kita sedang bernafas.
Islam bagi kaum sarungan adalah “darah dan daging”; ia mengalir tenang, kultural, dan selesai dengan dirinya sendiri. Kita tidak butuh label formal untuk merasa saleh.
Sebaliknya, ICMI pada masa awalnya dipenuhi oleh wajah-wajah baru. Mereka adalah teknokrat, insinyur, dokter, dan birokrat didikan Barat yang mengalami spiritual reawakening. Sosiolog menyebut mereka “Santri Baru”. Mereka memiliki ghirah (semangat) yang meledak-ledak, namun seringkali gagap dalam turats (tradis keilmuan Islam).
Mereka memandang agama dengan logika teknik: hitam-putih, linear, dan formalistik. Mereka ingin “meng-Islam-kan” segala hal, mulai dari bank hingga ilmu pengetahuan, seolah-olah tanpa label “syariah”, segalanya menjadi haram.
Ketimpangan nalar ini terekam abadi dalam sebuah anekdot satir yang melegenda. Alkisah, seorang Kiai NU sedang berbincang dengan seorang petinggi ICMI yang baru mendalami Islam. Sang Kiai, dengan kerendahan hati khas pesantren, bercerita tentang putranya yang baru saja mengkhatamkan hafalan Al-Qur’an 30 juz.
Sang petinggi ICMI, dengan antusiasme yang tulus namun naif, menepuk bahu sang Kiai dan berkata, “Luar biasa! Hebat sekali anak Pak Kiai. Terus, tinggal berapa juz lagi yang belum dihafal?”
Sang Kiai hanya tersenyum simpul. Ia tahu, tamunya sedang menggunakan logika “proyek bendungan” untuk memahami samudera wahyu. Tamunya mengira Al-Qur’an adalah ensiklopedia berjilid-jilid yang bisa ditambah volumenya jika anggaran turun. Anekdot ini lucu, tapi sekaligus tragis.
Ia menelanjangi sebuah realitas pahit: betapa semangat beragama seringkali tidak dibarengi dengan peta jalan pengetahuan yang memadai. Ada “gegar epistemologi” yang serius di sana.
Dan hari ini, puluhan tahun setelah anekdot itu lahir, apakah keadaan sudah berubah?
Rasanya kita justru sedang mengalami deja vu. Fenomena “Cendekiawan Muslim” yang hanya sebatas label masih menjamur, bahkan bermutasi menjadi lebih banal. Kita melihat banyak tokoh bergelar profesor di bidang non-agama yang tiba-tiba mendadak menjadi mufti di media sosial.
Mereka berbicara soal hukum Tuhan dengan modal terjemahan mesin pencari, tanpa mengerti asbabun nuzul, tanpa memahami maqasid syariah, dan yang paling parah: tanpa memiliki dzauq (rasa) kemanusiaan.
Mereka adalah “Cendekiawan Muslim” dalam arti sosiologis—orang Islam yang jadi cendekiawan—bukan dalam arti intelektual otentik. Gelar akademik mentereng seringkali menutupi kekosongan nalar keagamaan mereka. Akibatnya, narasi Islam yang mereka bawa ke ruang publik menjadi kaku, kering, dan tak jarang memicu konflik.
Mereka sibuk memoles “gincu” agama agar terlihat merah merona di bibir kekuasaan, sementara “garam” agama—yakni nilai keadilan dan kemanusiaan—justru mereka lupakan.
Sebagai anak kandung tradisi, alumni Aqidah dan Filsafat, dan kader Mathla’ul Anwar yang dididik untuk menyalakan cahaya (bukan sekadar memantulkan cahaya), saya punya tugas sejarah, yang harus berani mengatakan bahwa Islam bukan sekadar identitas yang ditempel di baju birokrasi. Islam adalah nilai yang harus hidup dalam etika publik.
Kita merindukan cendekiawan yang tidak bertanya “tinggal berapa juz lagi?”, melainkan cendekiawan yang bertanya “apa yang bisa kita perbuat dengan 30 juz ini untuk memanusiakan manusia?”.
Kita butuh mereka yang berislam secara substantif, bukan simbolik. Kita butuh garam yang larut memberi rasa, bukan gincu yang hanya tebal di permukaan tapi luntur saat tersapu air mata penderitaan rakyat.
Mari kita kembali ke khittah akal sehat. Sebab tanpa nalar yang jernih, agama hanya akan menjadi pentungan di tangan orang yang sedang mabuk kekuasaan, bukan menjadi pelita bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Wallahualam.
*
Penulis adalah Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (LIBAS). Liberal kependekan dari Lintas Iman, Budaya, Etnis, Ras, dan Lainnya.